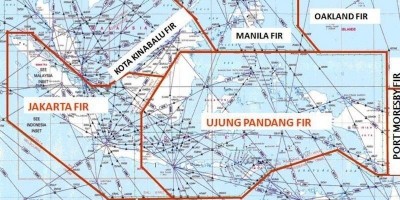Oleh: Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
LIMA tahun lalu, KAMI berdiri dengan suara yang lantang: suara moral. Gerakan itu menolak tunduk pada arus besar kekuasaan, menolak diam di tengah kezaliman yang diam-diam mengakar. Ia lahir dengan keyakinan bahwa demokrasi bisa diselamatkan bukan dengan amarah, melainkan dengan ingatan—bahwa negeri ini pernah memiliki cita-cita luhur: keadilan dan kebebasan.
Tapi apa yang disebut “gerakan moral” sering kali diuji justru ketika penguasa berganti. Jokowi telah lengser, tetapi apakah kekuasaannya ikut pergi? Bayang-bayang itu masih ada, menjelma dalam sosok anaknya yang kini duduk di samping presiden terpilih, Prabowo Subianto. Seakan sejarah menolak menutup babak lama.
Di masa Jokowi, KAMI hidup dalam tekanan. Aktivisnya diburu, sebagian dijebloskan ke penjara. Aparat hukum dijadikan cambuk, bukan untuk meluruskan, tetapi untuk menundukkan. Namun, justru dalam tekanan itu KAMI memperoleh makna: ia berdiri sebagai saksi bahwa suara yang benar tidak bisa dipadamkan oleh represi.
Kini, di masa Prabowo, situasinya lain—tapi juga sama berat. Harapan baru terbit, tetapi wajah lama ikut mengiringi. Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Rakyat melihat kabinet gemuk, koalisi besar, dan narasi persatuan yang dibangun di atas kompromi elite. Tetapi mereka juga tahu, persatuan tanpa keadilan hanya akan menjadi gedung megah yang berdiri di atas tanah rapuh.
“Tidak ada revolusi yang lebih mendesak daripada revolusi moral,” tulis Soekarno dalam salah satu pidatonya. Kata-kata itu kini seakan mengingatkan KAMI: fondasi bangsa tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh apakah kekuasaan itu adil.
Moral selalu penting. Ia memberi ukuran. Ia menjaga agar bangsa tak kehilangan arah. Tetapi moral tanpa daya untuk mengubah sering kali hanya menjadi renungan yang sunyi.
KAMI bisa memilih tetap menjadi “hati nurani bangsa”—tetapi hati nurani itu mungkin akan terdengar samar di tengah gegap-gempita politik yang kian pragmatis. Atau ia bisa melangkah lebih jauh: mendorong pemakzulan Wapres, mengusulkan pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, menuntut lembaga antikorupsi kembali berdaulat, atau membangun blok moral yang menegaskan bahwa presiden harus berdaulat penuh—tanpa bayang-bayang dinasti.
Vaclav Havel, presiden Ceko yang juga penyair, pernah berkata: “Kebenaran dan cinta harus menang atas kebohongan dan kebencian.” Tetapi sejarah juga membuktikan, kebenaran hanya bisa menang bila ia dipadukan dengan organisasi, strategi, dan keberanian politik.
Sejarah memberi banyak ilustrasi. *Solidarność* di Polandia lahir sebagai serikat buruh yang hanya menuntut martabat pekerja, tetapi berubah menjadi mesin politik yang meruntuhkan Partai Komunis. *Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat dari Martin Luther King Jr* awalnya seruan moral di mimbar gereja, namun berkembang menjadi pengungkit yang melahirkan Civil Rights Act dan Voting Rights Act. Perlawanan *anti-apartheid oleh Nelson Mandela* di Afrika Selatan dimulai sebagai teriakan moral, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan politik yang menumbangkan rezim diskriminatif dan mengubah wajah negeri. Dan di sini, Reformasi 1998 adalah bukti bahwa suara mahasiswa yang bermula sebagai seruan moral bisa mengguncang istana, menumbangkan Orde Baru, dan membuka jalan bagi demokrasi.
Moral di situ tidak berhenti sebagai doa; ia berubah menjadi daya yang menggerakkan bangsa.
Pertanyaannya, bagaimana “memisahkan” Prabowo dari Gibran—dari bayangan Jokowi yang terus mengiringi? Itu bukan soal fisik atau jabatan, melainkan soal legitimasi.
Prabowo hanya akan benar-benar berdiri sebagai presiden berdaulat bila ia berani memilih: bersama rakyat atau bersama bayang-bayang dinasti. Caranya? Dengan opini publik yang mendesak. Dengan agenda konkret yang memaksa presiden menentukan sikap. Dengan konsensus moral dari tokoh-tokoh bangsa yang menyuarakan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan bila presiden tak menjadi perpanjangan tangan siapa pun.
“Demokrasi tidak bisa bertahan tanpa kepercayaan publik,” kata Hatta. Kepercayaan itu tak lahir dari janji politik, melainkan dari keberanian untuk melawan kekuasaan yang menyimpang.
Mungkin inilah paradoks KAMI hari ini: ia lahir sebagai gerakan moral, tetapi justru akan kehilangan makna bila hanya berhenti di situ. Masa depan KAMI mungkin bukan lagi sekadar menjadi saksi, tetapi juga menjadi pengungkit.
Persatuan nasional yang sesungguhnya hanya bisa terwujud bila dua fondasi itu hadir: keadilan dan kepercayaan. Dan keduanya tak mungkin lahir bila kekuasaan terus terjerat dalam lingkar dinasti.
KAMI bisa memilih tetap diam dalam kemurnian moral, atau mengambil risiko menantang realitas politik. Apa pun pilihannya, satu hal pasti: masa depan demokrasi Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari keberanian untuk berkata benar—sekalipun kebenaran itu berhadapan dengan presiden, atau dengan bayang-bayangnya.