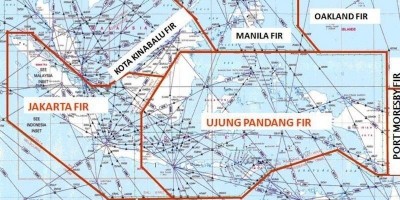Oleh: Perdana Wahyu Santosa, Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Peneliti Senior GREAT Institute
INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang krusial. Pertumbuhan ekonomi yang beberapa tahun terakhir relatif stabil mulai menghadapi tantangan serius akibat gejolak politik domestik.
Ketidakpastian kebijakan, meningkatnya intensitas demonstrasi di berbagai daerah, serta polarisasi politik yang semakin tajam, menjadi faktor yang membebani iklim usaha. Investor, baik dalam negeri maupun asing, cenderung bersikap menunggu (wait and see) untuk memastikan arah kebijakan pemerintah.
Kondisi ini memperlambat arus investasi baru dan menekan daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia yang relatif lebih stabil. Dalam konteks ekonomi politik, ketidakpastian politik sering kali lebih berbahaya daripada krisis ekonomi itu sendiri, karena menimbulkan keraguan jangka panjang.
Stabilitas politik seharusnya menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan berkelanjutan, namun ketika arena politik lebih sering dipenuhi konflik terbuka, ekonomi pun rentan terhadap guncangan eksternal maupun internal.
Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini, bahkan mengarah aksi anarkis yang sistemik, tidak hanya merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap isu-isu spesifik, tetapi juga menunjukkan adanya kegelisahan struktural dalam masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan rakyat kecil, terutama terkait inflasi pangan, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial.
Di sisi lain, keterlibatan interest groups dalam dinamika politik sering kali memperkeruh situasi. Dampaknya, demonstrasi bukan hanya menjadi ekspresi demokrasi, tetapi juga alat tekanan politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Jika situasi ini tidak dikelola dengan cepat dan bijak maka ada risiko meningkatnya distrust antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan apa yang disebut high cost politics—di mana proses politik menjadi mahal, penuh kompromi, dan akhirnya mengurangi ruang fiskal serta kapasitas negara untuk mendorong pembangunan. Sektor keuangan dan investasi adalah pihak pertama yang paling peka terhadap gejolak politik.
Fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah belakangan ini menunjukkan korelasi erat dengan intensitas aksi massa dan dinamika politik di parlemen. Investor asing, misalnya, sangat memperhatikan stabilitas regulasi dan kepastian hukum. Ketika wacana perubahan kebijakan atau tarik-menarik kepentingan politik terjadi di ruang publik, pasar langsung bereaksi negatif.
Hal yang sama berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri. Mereka akan menunda ekspansi, merevisi rencana bisnis, bahkan melakukan capital flight jika situasi politik dianggap tidak kondusif. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kehilangan momentum investasi bisa berarti tertinggal beberapa tahun bahkan hingga satu dekade.
Inilah risiko laten yang sering diabaikan: politik yang gaduh bisa menelan habis seluruh potensi bonus demografi dan peluang emas Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang naik daun. Namun, tidak semua harus dilihat secara pesimistis.
Sejarah menunjukkan bahwa gejolak politik sering menjadi katalis bagi lahirnya reformasi besar dalam perekonomian Indonesia. Reformasi 1998 adalah contoh paling nyata bagaimana krisis politik-ekonomi membuka ruang bagi perubahan fundamental, mulai dari demokratisasi hingga deregulasi ekonomi.
Tantangan hari ini bisa menjadi peluang serupa, asalkan elite politik dan pemangku kebijakan mampu menjadikannya momentum korektif. Rakyat Indonesia semakin kritis, terhubung melalui media sosial, dan menuntut akuntabilitas lebih tinggi dari pemerintah maupun swasta.
Jika aspirasi ini direspon dengan inklusi, transparansi, dan konsistensi kebijakan, maka gejolak politik justru bisa menjadi jalan bagi penguatan institusi ekonomi. Di sinilah pentingnya melihat krisis bukan hanya sebagai ancaman, melainkan juga sebagai pintu menuju tatanan baru yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Meski demikian, realitas saat ini menunjukkan adanya jurang antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan. Banyak kebijakan yang bersifat populis, namun belum memiliki basis ekonomi yang kuat.
Misalnya, program subsidi yang diperluas kurang memperhitungkan beban fiskal jangka panjang, atau proyek infrastruktur yang terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik lokal. Kesenjangan yang terjadi antara wacana dan pelaksanaan inilah yang berpotensi memperparah ketidakpuasan publik.
Dalam literatur ekonomi politik, situasi ini disebut sebagai policy inconsistency—di mana tujuan jangka pendek mencederai visi jangka panjang. Ketika kebijakan berubah-ubah dan berkompromi dengan tekanan politik, maka pasar kehilangan arah dan masyarakat kehilangan kepercayaan.
Jika tidak segera diperbaiki, ketidakkonsistenan ini dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang sulit keluar dari stagnasi.
Selain inkonsistensi kebijakan, persoalan lain yang memperburuk suasana adalah buruknya sensitivitas dan komunikasi publik DPR.
Di tengah rakyat yang menghadapi tekanan ekonomi akibat harga kebutuhan pokok yang naik, khususnya beras dan lapangan kerja yang terbatas, sering kali pernyataan anggota parlemen justru terdengar tidak empatik, kenaikan tunjangan yang fantastis, berjoget ria di parlemen bahkan melakukan flexing yang cenderung mencederai perasaan masyarakat.
Alih-alih menunjukkan empati, banyak pernyataan yang terkesan elitis, normatif, atau hanya membela kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, jurang psikologis antara rakyat dan wakil rakyat semakin melebar.
Dalam teori politik, komunikasi publik seharusnya menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan (trust-building mechanism). Namun ketika jembatan itu rusak karena miskomunikasi atau ketidakpekaan atau ketidakpedulian, maka legitimasi politik DPR ikut terkikis.
Dampaknya bukan hanya pada citra lembaga, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, karena ketidakpercayaan publik bisa bertransformasi menjadi resistensi sosial yang menghambat setiap agenda pembangunan.
Faktor global juga memperberat situasi. Perlambatan ekonomi Tiongkok, kenaikan suku bunga The Fed, perdagangan internasional dan ketegangan geopolitik dunia memberi tekanan tambahan terhadap perekonomian domestik.
Dalam keadaan normal, Indonesia masih bisa menahan guncangan eksternal tersebut dengan instrumen fiskal dan moneter. Namun dalam kondisi politik yang bising, kemampuan pemerintah untuk merespons secara cepat dan tepat menjadi terbatas.
Setiap kebijakan bisa dipolitisasi, setiap langkah bisa ditarik ke dalam perdebatan partisan. Inilah titik lemah Indonesia saat ini: kapasitas teknokratis yang kuat kerap tereduksi oleh kompromi politik. Padahal, ekonomi Indonesia sangat membutuhkan stabilitas untuk menjaga kepercayaan investor, memperluas ekspor, serta memperkuat cadangan devisa. Tanpa itu, defisit transaksi berjalan dan ketergantungan pada utang luar negeri bisa kembali menghantui.
Rekomendasi Indonesia jelas membutuhkan jalan keluar yang realistis agar ekonomi tidak terus-menerus tersandera oleh politik. Gejolak politik memang bagian dari dinamika demokrasi, namun harus dikelola agar tidak merusak fondasi ekonomi. Para pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan masyarakat sipil—harus menyadari bahwa stabilitas politik adalah aset ekonomi terbesar bangsa ini.
Untuk itu, ada tiga rekomendasi strategis yang perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah dan parlemen harus menegakkan konsistensi kebijakan dengan memperkuat kepastian hukum dan regulasi.
Kedua, elite politik perlu mengedepankan dialog inklusif, bukan mobilisasi massa, dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan.
Ketiga, dunia usaha dan akademisi harus lebih proaktif memberikan masukan berbasis data agar kebijakan ekonomi tidak semata populis, tetapi juga berkelanjutan. Jika langkah-langkah ini ditempuh, maka Indonesia bukan hanya mampu keluar dari situasi kurang kondusif saat ini, tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai kekuatan ekonomi-politik yang matang di Asia.