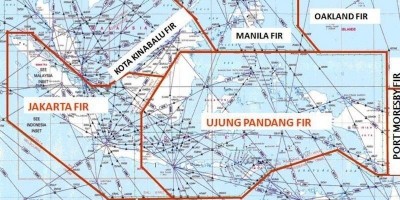Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
APBN Bisa Menelan Kenaikan MBG Tanpa “Tersedak”?
Pertanyaannya sederhana namun tajam: ketika anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak dari sekitar Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun, mampukah APBN menanggungnya tanpa menggerus prioritas lain dan tanpa menarik utang secara berlebihan? Inilah rumusan masalah yang perlu dijawab dengan data.
Di satu sisi, tekad memperbaiki gizi dan kualitas SDM adalah investasi sosial yang tidak boleh ditawar.
Di sisi lain, ruang fiskal kita tidak tak terbatas. Belanja negara 2026 dipatok sekitar Rp3.786,5 triliun dengan defisit 2,48% PDB; pendidikan 20% konstitusional mencapai Rp757,8 triliun.
Di tengah postur itu, MBG mendekati 9% dari total belanja dan setara lebih dari 40% anggaran pendidikan.
Tekanan terhadap komponen belanja lain—khususnya belanja modal dan sebagian pos diskresioner—menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi, bukan diingkari.
Bayangkan negara sebagai rumah tangga dengan dapur raksasa.
Tahun depan, dapur ini harus memasak untuk 82,9 juta penerima; ongkos hariannya kira-kira Rp1,2 triliun, atau sekitar Rp25 triliun per bulan.
Jika pemasukan tidak naik sebanding, opsi yang tersisa biasanya tiga: menunda renovasi rumah (infrastruktur), mengurangi uang belanja anak-anak di daerah (transfer ke daerah), atau menggesek kartu kredit (menerbitkan utang) dengan bunga yang akan menjadi beban esok hari.
Kita melihat gejala ketiganya: rencana pembiayaan utang bruto mendekati rekor, ruang belanja modal cenderung menyempit, dan transfer ke daerah berpotensi disesuaikan untuk menciptakan ruang bagi prioritas pusat.
Analogi ini mengingatkan bahwa MBG, betapapun mulia tujuannya, adalah proyek logistik dan tata kelola yang besar, bukan sekadar belanja menu makan.
Risiko Fiskal: Nyata, Tetapi Dapat Dikelola
Kenaikan MBG mempersempit “fiscal space” pada pos yang tidak dilindungi mandat hukum.
Pendidikan aman karena 20% UUD, tetapi infrastruktur fisik, program lintas kementerian, atau sebagian alokasi ke daerah berpotensi menjadi bantalan penyesuaian jika penerimaan negara meleset dari target.
Ketergantungan pada pembiayaan utang juga meningkat. Di era suku bunga global yang belum sepenuhnya reda, biaya dana berpotensi menanjak dan beban bunga akan menyita porsi belanja esok hari.
Selain itu, risiko implementasi tidak kecil: pasokan bahan baku, standar kualitas dan keamanan pangan, hingga pencegahan kartelisasi pemasok lokal.
Skala besar membuat kesalahan kecil berubah menjadi kebocoran besar ketika diduplikasi jutaan kali. Tanpa arsitektur pengawasan yang baik, niat mulia dapat kehilangan efektivitas.
Efektivitas Ekonomi: Dari “Perputaran Uang” ke Nilai Tambah
Klaim perputaran ekonomi MBG yang sudah puluhan triliun pada fase awal memberi sinyal dampak positif di hilir: UMKM pangan hidup, jasa angkut bergerak, serta pembangunan dan operasional SPPG menciptakan aktivitas lokal.
Namun sebagai ekonom, saya mengingatkan bahwa “perputaran” berbeda dengan nilai tambah (PDB). Untuk menilai kontribusi bersih terhadap perekonomian, kita perlu memisahkan kandungan impor, margin distribusi, upah, dan laba, lalu menghitung efek lanjutan konsumsi pekerja.
Barulah terlihat berapa dampak riil ke PDB dan pengurangan kemiskinan.
Di sisi lain, manfaat terbesar MBG justru berada di jangka menengah: ketidakhadiran menurun, anemia turun, fokus belajar naik, dan hasil belajar membaik.
Itulah “dividen gizi” yang berubah menjadi “dividen produktivitas” beberapa tahun kemudian.
Namun klaim ini harus disokong evaluasi yang serius: randomized rolloutlintas kabupaten, baseline jelas, dan dashboard indikator yang dipublikasikan berkala.
Menyederhanakan Aritmetika, Menjaga Transparansi
Dengan Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima, alokasi rata-rata per orang sekitar Rp4,04 juta per tahun.
Jika layanan efektif 200–220 hari sekolah, biaya per hari berada di kisaran Rp18–20 ribu; jika diasumsikan 365 hari, sekitar Rp11 ribu.
Perbedaan asumsi hari layanan inilah yang sering memicu perdebatan angka harian atau bulanan.
Jalan keluarnya sederhana: pemerintah perlu menstandardisasi dan mempublikasikan asumsi hari layanan, paket gizi, serta komponen biaya logistik agar publik memahami logika angkanya dan mempercayai eksekusinya.
Tiga Pengaman Kebijakan agar APBN Tidak “Tersengal”
Pertama, tetapkan _fiscal guardrails_ untuk MBG: plafon dinamis sebagai persentase belanja negara yang ikut menyesuaikan realisasi penerimaan.
Ketika penerimaan melemah, program menurunkan volume secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas, bukan langsung memotong investasi produktif.
Kedua, lindungi belanja modal dan rapikan arsitektur pusat–daerah. Infrastruktur konektivitas pangan—dari jalan lokal hingga cold chain—adalah syarat agar MBG tidak memicu inflasi pangan lokal.
Transfer ke daerah untuk fungsi pengawasan dan layanan dasar perlu dirancang ulang dengan service level yang jelas, bukan sekadar ditekan.
Ketiga, gunakan pembiayaan berbiaya murah dan terkelola: perkuat basis investor domestik, manfaatkan thematic bonds untuk infrastruktur gizi, dan disiplin pada tenor untuk menghindari penumpukan jatuh tempo.
Jangan Nafsu Harus Nafas Panjang untuk Generasi Emas
MBG adalah investasi sosial yang seharusnya tidak terburu-buru, tetapi keberhasilan sejatinya ditentukan oleh disiplin fiskal dan ketelitian eksekusi.
Kita ingin dua dividen sekaligus: dividen gizi hari ini dan dividen produktivitas esok.
Itu hanya terjadi bila tiap rupiah yang dibelanjakan memperkuat nilai tambah domestik tanpa melemahkan tulang punggung pertumbuhan, yakni infrastruktur dan kemampuan fiskal yang sehat.
Dengan pengaman kebijakan yang jelas, transparansi aritmetika, dan evaluasi dampak yang jujur, lonjakan MBG tidak harus menjadi beban; ia dapat menjadi lompatan yang mengantar Indonesia pada generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing, tanpa membuat APBN kehabisan napas.