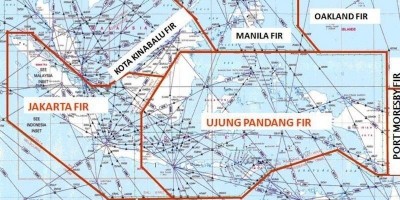Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
MALAM 28 Agustus 2025 mencatat luka baru bagi demokrasi Indonesia. Seorang pemuda berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, pekerja keras yang sehari‑hari menjadi pengemudi ojek online (ojol), pulang tak bernyawa.
Ia baru saja mengantarkan pesanan dan hendak menjemput penumpang ketika demonstrasi menuntut perbaikan upah dan menolak tunjangan mewah wakil rakyat berubah menjadi chaos.
Menurut sang ibu, Erlina, Affan adalah tulang punggung keluarga; ia menabung untuk membeli lahan dan membangun rumah untuk orang tuanya di Lampung. Ketika kerusuhan pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat, kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) menerobos kerumunan dan melindas motornya.
Video di media sosial memperlihatkan kendaraan itu menabrak Affan, sempat melambat, lalu kembali mempercepat laju dan meninggalkan korban. Tujuh petugas kini ditahan, tetapi nyawa tak bisa dikembalikan dan duka keluarga belum terobati.
Tragedi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa aparat yang ditugasi melindungi malah menyebabkan korban jiwa? Mengapa seorang pekerja yang tidak ikut berunjuk rasa justru menjadi korban terburuk dari benturan aparat dan massa?
Saya melihat peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi gejala dari kombinasi kelalaian prosedural, kultur kekerasan, dan tata kelola anggaran yang menyimpang.
Dari sini, kita perlu merefleksikan tiga hal: kesalahan penanganan, ironi anggaran Polri yang sangat besar, dan urgensi evaluasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Tragedi Affan: Cermin Kegagalan Manajemen Kerumunan
Demonstrasi yang terjadi pada 28 Agustus merupakan aksi kedua dalam satu pekan yang dipicu paket tunjangan untuk anggota DPR—50 juta rupiah untuk perumahan, 12 juta untuk makan, 7 juta untuk transportasi, jauh di atas upah minimum.
Massa pekerja dan mahasiswa menuntut upah layak, menolak outsourcing, dan memprotes pajak daerah yang naik hingga 250 persen.
Di tengah tuntutan itu, aparat berseragam lengkap, membawa kendaraan taktis, menyemprotkan meriam air dan menembakkan gas air mata.
Video memperlihatkan mobil Brimob menerobos kerumunan, padahal warga sudah memberi peringatan. Bukannya berhenti, kendaraan itu melaju dan melindas Affan.
Kesalahan penanganan tidak berhenti pada satu kendaraan. Laporan Reuters menyebut ratusan mahasiswa dan pengemudi ojol berunjuk rasa di depan markas Brimob sampai dini hari. Polisi melepaskan gas air mata dan meriam air, sementara 600 orang dilaporkan ditangkap.
Presiden Prabowo Subianto mengaku “terkejut dan kecewa” atas tindakan aparat, memerintahkan investigasi dan meminta penegakan hukum terhadap pelaku. Kepala Polda Metro Jaya Asep Edi Suheri bahkan meminta maaf secara terbuka dan membenarkan bahwa Affan bukan bagian dari aksi.
Namun permintaan maaf tak menghapus kesan penanganan brutal. Banyak analis dan publik di sosial media menyebut tindakan tersebut bukan kecelakaan melainkan “tindakan brutal” yang melanggar prosedur.
Di sini tampak kelemahan pendekatan aparat. Polisi berperan sebagai penjaga ketertiban dan pelindung warga, bukan pasukan tempur.
Namun dalam banyak aksi, pendekatan yang diambil cenderung militeristik: penggunaan kendaraan lapis baja, senjata huru‑hara, dan taktik tekanan.
Analoginya seperti dokter yang menangani demam dengan amputasi—masalah ketertiban diselesaikan dengan kekerasan berlebihan.
Tidak heran apabila Amnesty International menyoroti tindakan yang tidak proporsional seperti gas air mata, pemukulan, dan penangkapan sewenang‑wenang sebagai pelanggaran hak berkumpul.
Memperbaiki Melalui Anggaran. Polri: Rumah Mewah Tanpa Pondasi
Ironi terbesar dari tragedi ini adalah kontras antara besarnya anggaran Polri dengan kualitas pelayanan publik dan pengamanan aksi.
Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Polri meningkat dari Rp102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp145,6 triliun untuk 2026.
Anggaran tahun 2026 diarahkan ke program profesionalisme SDM (Rp1,2 triliun), penyelidikan (Rp3,6 triliun), modernisasi alat utama dan sarana prasarana (Rp52,7 triliun) serta dukungan manajemen yang mencapai Rp73 triliun.
Realisasi belanja 2025 hingga Juni baru 48,67 persen dengan penyerapan Rp69,1 triliun.
Selain itu, Polri meminta tambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Publik mempertanyakan justifikasi tambahan itu karena porsi terbesar adalah belanja barang dan modal—area yang rentan korupsi. Publik juga mencatat bahwa 46 persen sentimen publik terhadap tugas pemeliharaan ketertiban negatif.
Permintaan naiknya anggaran 37 persen—dari Rp126,6 triliun menjadi Rp173,4 triliun tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah. Dana besar seharusnya dialihkan ke pendidikan atau bantuan sosial.
Sayangnya, transparansi penggunaan anggaran Polri minim. Program “dukungan manajemen” bernilai Rp73 triliun tidak dijelaskan rinci. Pada saat yang sama, Polri memamerkan robot polisi seharga hampir Rp3 miliar per unit dalam upacara HUT Bhayangkara Juli 2025 lalu.
Analogi rumah mewah dengan atap bocor sangat relevan: institusi ini berinvestasi pada teknologi canggih dan kendaraan lapis baja, tetapi gagal menyediakan prosedur pengamanan yang sederhana—seperti memastikan kendaraan taktis tidak melindas warga.
Anggaran besar yang tak terarah hanya memperbesar potensi penyimpangan dan memperparah ketidakpercayaan publik.
Kesalahan Fatal dalam Menghadapi Demonstrasi: Pelajaran dari Affan
Apa saja kesalahan aparat dalam demonstrasi yang merenggut nyawa Affan?
Pertama, kegagalan identifikasi risiko.
Demonstrasi di depan parlemen sudah berlangsung sejak pagi, dan massa terdiri dari buruh, mahasiswa, serta warga sekitar. Kehadiran ojol seperti Affan seharusnya diduga karena jalan raya adalah tempat mereka mencari nafkah.
Namun aparat tidak membuat jalur evakuasi atau “safe zone” bagi warga non‑demonstran.
Kedua, penggunaan kendaraan berat di area padat.
Mobil taktis Brimob berfungsi untuk situasi terorisme atau kerusuhan ekstrem, bukan untuk membelah kerumunan sipil.
Video menunjukkan pengemudi mobil tidak mengurangi kecepatan meski ada peringatan. Ini melanggar prinsip dasar pengendalian massa yang mengutamakan keselamatan.
Ketiga, ketidakpatuhan terhadap eskalasi bertahap.
Dalam manual pengamanan aksi damai, penggunaan gas air mata dan meriam air adalah tindakan setelah negosiasi dan peringatan.
Namun laporan saksi di lapangan melaporkan aparat langsung menembakkan gas air mata dan meriam air saat bentrok berlangsung.
Ketika kekerasan menjadi respon pertama, aksi damai berubah menjadi kerusuhan, dan orang yang tidak terlibat menjadi korban.
Keempat, ketiadaan komunikasi dan koordinasi. Aparat dan koordinator aksi seharusnya membangun kanal komunikasi.
Tanpa itu, misinformasi mudah menyebar dan aparat hanya mengandalkan instruksi satu arah. Ketika demonstran meneriakkan “keadilan untuk Affan” dan “nyawa dibalas nyawa”, situasi sudah kehilangan kendali.
Keterlambatan polisi dalam memberi informasi dan permintaan maaf memperbesar kecurigaan dan kemarahan publik.
Mengapa Evaluasi Besar Diperlukan?
Kematian Affan memicu kemarahan nasional bukan semata karena tragedi itu sendiri, tetapi karena ia menjadi simbol kegagalan berulang.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat serangkaian kasus kekerasan aparat saat menghalau demonstrasi, dari bentrokan mahasiswa hingga tragedi Kanjuruhan (pengetahuan umum). Bila hal ini dibiarkan, legitimasi Polri sebagai penegak hukum akan terkikis.
Evaluasi besar di tubuh Polri diperlukan karena tiga alasan:
Pemulihan kepercayaan publik. Data ICW menunjukkan hampir setengah masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap kinerja pemeliharaan ketertiban.
Tanpa kepercayaan, legitimasi kekuasaan bersenjata rapuh. Evaluasi menyeluruh harus mengaudit tidak hanya pelanggaran individu, tetapi juga kultur organisasi, pola perekrutan, dan mekanisme penegakan disiplin.
Efektivitas penggunaan anggaran. Dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah dan permintaan tambahan puluhan triliun, Polri wajib memastikan setiap rupiah berkontribusi pada keamanan publik.
Evaluasi harus menelaah apakah belanja modal seperti kendaraan lapis baja dan robot benar‑benar dibutuhkan, atau justru memperbesar jarak antara polisi dan masyarakat.
Penataan ulang paradigma keamanan. Polri masih menganut paradigma keamanan internal yang memprioritaskan ketertiban di atas hak warga.
Padahal UU No 9/1998 menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum. Amnesty International menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus perlu, proporsional dan akuntabel.
Evaluasi harus merumuskan ulang standar operasional, menjadikan de‑eskalasi dan perlindungan hak asasi sebagai prioritas.
Rekomendasi untuk Membangun Polisi Pro‑Publik
Bagaimana langkah konkret untuk memperbaiki situasi? Beberapa rekomendasi berikut dapat menjadi agenda evaluasi besar:
Audit dan transparansi anggaran. Publikasikan secara rinci pos anggaran Polri, terutama program “dukungan manajemen” bernilai puluhan triliun. Namun proses ini sulit dilakukan. Harus juga libatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan partisipasi publik dalam proses evaluasi.
Korupsi hanya berkembang dalam kegelapan; transparansi adalah cahaya.
Perombakan pelatihan pengamanan massa. Modul pelatihan harus memprioritaskan teknik negosiasi, komunikasi massa, dan de‑eskalasi.
Penggunaan kendaraan taktis harus dibatasi dan dipersyaratkan hanya untuk situasi luar biasa. Kesalahan prosedural dalam kasus Affan menjadi bukti bahwa pelatihan belum sejalan dengan prinsip HAM.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal. Propam (profesi dan pengamanan) harus diberi kewenangan dan kemandirian lebih untuk menindak pelanggaran.
Di sisi eksternal, komisi kepolisian nasional dan lembaga hak asasi harus dilibatkan dalam investigasi. Penanganan kasus Affan harus menjadi contoh keterbukaan: proses hukum yang transparan terhadap tujuh oknum, bukan sekadar sanksi etik.
Pendekatan berbasis komunitas. Polri perlu mereorientasi tugas dari “penjaga” menjadi “pelayan”. Program Bhabinkamtibmas yang mendekatkan polisi ke desa perlu diperkuat, bukan sekadar retorika. Polisi yang mengenal masyarakatnya cenderung mengedepankan dialog ketimbang represi.
Pengalihan fokus belanja dari alat berat ke SDM. Daripada membeli robot mahal atau kendaraan taktis, alokasi sebaiknya diarahkan pada kesejahteraan anggota, pelatihan, kesehatan mental, dan teknologi informasi yang meningkatkan pelayanan.
Data menunjukkan porsi belanja personel hanya Rp35,9 triliun dari realisasi 2025, sementara belanja modal Rp20 triliun. Keseimbangan perlu diperbaiki agar investasi terbesar berada pada manusia, bukan mesin.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan SOP. Aktivis, akademisi, dan komunitas korban harus dilibatkan dalam merumuskan pedoman pengamanan aksi.
Keterlibatan ini mencegah terulangnya tragedi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap Polri.
Dukungan bagi korban dan keluarga. Negara berkewajiban memberi kompensasi, perlindungan, dan akses keadilan bagi keluarga Affan dan korban lain.
Presiden Prabowo telah menyatakan rasa duka dan memerintahkan penyelidikan; langkah ini harus diikuti tindak lanjut berupa ganti rugi dan jaminan pendidikan bagi adik‑adik Affan.
Mengubah Derita Menjadi Agenda Reformasi
Kematian Affan Kurniawan mengguncang nurani bangsa karena ia merangkum ketidakadilan struktural: warga kecil menjadi korban perseteruan elit dan aparat, anggaran triliunan rupiah tidak menjamin keselamatan, dan budaya kekerasan mengalahkan nilai kemanusiaan.
Tragedi ini layaknya cermin yang memantulkan wajah buram institusi keamanan kita. Apa gunanya kendaraan lapis baja, robot canggih, dan anggaran raksasa jika seorang pemuda pencari nafkah tidak bisa pulang dengan selamat?
Evaluasi besar di tubuh Polri bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan moral. Tanpa perubahan mendasar—transparansi anggaran, reformasi pelatihan, pengawasan kuat, dan reorientasi paradigma—tragedi serupa akan terulang. Affan bukan nama terakhir bila sistem dibiarkan.
Menurut saya, evaluasi di tubuh Polri tidak efektif dilakukan manakala tidak dilakukan perubahan kepemimpinan. Transformasi leadership adalah syarat mutlak evaluasi dan perubahan dapat dilakukan dengan baik. Ini menjadi PR Pak Prabowo.
Sebaliknya, jika kita mampu belajar dari derita ini, memperbaiki cara berfikir dan bertindak, kita bisa membangun kepolisian yang benar‑benar melayani dan melindungi. Marilah menjadikan darah Affan sebagai cahaya perubahan, bukan sekadar kisah sedih yang hilang ditelan waktu.