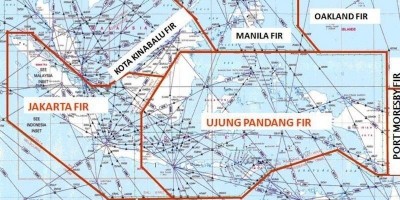Oleh: Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS)
KETIKA memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia setara dengan negara-negara yang kini telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi Asia, seperti Korea Selatan. Namun, di usianya yang ke-80, kita seringkali tampak seperti negara yang baru berdiri dalam hal moralitas politik dan tata kelola pemerintahan, dengan pola pikir kolonial yang mengakar kuat.
Generasi 1945 berjuang untuk kemerdekaan dengan tombak bambu dan persatuan lintas etnis. Generasi saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi yang mengakar, politik yang hanya menguntungkan segelintir elit, dan pemerintahan yang semakin jauh dari rakyat.
Krisis kita bukan hanya ekonomi atau politik, tetapi juga melibatkan hilangnya arah moral. Ketika kaum elit menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, ketika hukum melayani penguasa, dan ketika kebijakan mengutamakan keuntungan politik jangka pendek, bangsa ini telah kehilangan arah.
Nilai-nilai ideologi negara Pancasila kini hanya slogan seremonial, dan keadilan sosial hanyalah retorika kampanye. Generasi muda tumbuh dengan pemahaman bahwa integritas jarang menang, sementara kompromi moral sering kali mengarah pada kekuasaan. Tanpa reformasi yang serius, kita berisiko membesarkan generasi yang apatis dan sinis yang tidak percaya pada demokrasi.
Meskipun para pendiri bangsa memandang politik sebagai mandat publik, elit saat ini sering melihatnya sebagai warisan. Dinasti politik merupakan fenomena umum: Dari tingkat nasional hingga daerah, jabatan diwariskan kepada anggota keluarga. Dalam pemilu, garis keturunan seringkali lebih penting daripada rekam jejak atau gagasan.
Hal ini menghambat meritokrasi, sehingga menyulitkan kaum muda yang cakap, kritis, dan berintegritas, tetapi tanpa koneksi finansial atau keluarga, untuk bergabung dengan partai politik. Banyak dari mereka justru memilih aktivisme nonpolitik, berwirausaha, atau beremigrasi.
Pemerintah bangga dengan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen yang tercatat pada kuartal kedua tahun 2025, tetapi masyarakat kesulitan merasakan dampaknya. Daya beli stagnan, harga pangan meningkat, dan pengangguran kaum muda tetap tinggi. Rupiah rentan terhadap nilai tukar sekitar Rp 16.000-16.200 terhadap dolar Amerika Serikat, dan utang pemerintah telah melampaui Rp 9 kuadriliun ($556,7 miliar) tanpa meningkatkan kapasitas ekonomi produktif.
Ketergantungan negara pada investasi asing semakin meningkat. Industri manufaktur, yang dulunya merupakan sumber utama lapangan kerja, melemah, tergeser oleh sektor pertambangan dan perkebunan yang padat modal dan hanya menciptakan sedikit lapangan kerja. Meskipun pembangunan infrastruktur sedang gencar, beberapa proyek hanya merupakan pajangan dengan dampak yang kecil dan luas, sementara yang lain terhenti karena perencanaan yang buruk.
Gerakan reformasi 1998 menjanjikan kebebasan sipil dan pemimpin yang bertanggung jawab. Dua puluh tujuh tahun kemudian, demokrasi kita masih ada, tetapi telah direduksi menjadi hiasan. Pemilu diadakan secara teratur, tetapi dirusak oleh praktik jual beli suara dan pengaruh birokrasi.
Kebebasan pers dijamin tetapi dibungkam melalui tekanan hukum, sensor halus, dan iklan pemerintah. Berbagai kasus pembubaran diskusi kampus, intimidasi jurnalis, dan kriminalisasi aktivis, menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi kita. Sebagian besar warga negara, yang telah terbiasa dengan kompromi politik, memandang hal ini sebagai hal yang "normal".
Saat dunia berpacu menuju revolusi teknologi, politik kita terperosok dalam perdebatan dangkal. Sementara negara-negara seperti Vietnam menarik investasi teknologi tinggi, Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Anggaran pendidikan terkikis oleh birokrasi, dan bonus demografi kita berisiko menjadi beban jika generasi muda kita tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar global.
Korupsi tetap menjadi momok terbesar. Laporan Transparency International tahun 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei, turun 19 peringkat dari peringkat ke-96 pada tahun 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan taringnya. Skandal seperti pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, dugaan korupsi di badan usaha milik negara, dan penyalahgunaan dana bantuan sosial hanyalah puncak gunung es. Pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus ini seringkali kembali berkuasa setelah menjalani hukuman penjara yang singkat, seolah-olah korupsi sama dengan “cuti sementara”.
Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo selama satu dekade telah meninggalkan warisan yang kompleks. Meskipun pembangunan infrastruktur besar-besaran terlihat jelas, banyak kebijakan strategis telah melemahkan lembaga-lembaga negara. KPK kehilangan independensinya, birokrasi terjerat kepentingan politik, dan kebebasan akademik ditekan.
Reformasi hukum terhenti dan hukum sering digunakan untuk menekan lawan. Kebijakan ekonomi seringkali berorientasi jangka pendek. Proyek-proyek unggulan seperti ibu kota baru dan kereta api cepat menghabiskan anggaran besar dengan manfaat langsung yang minimal bagi warga negara.
Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto mewarisi anggaran yang ketat dan utang yang tinggi. Investasi asing seringkali berfokus pada ekstraksi sumber daya dan kurangnya transfer teknologi yang berarti, sementara kebijakan yang longgar seringkali mengorbankan perlindungan lingkungan.
Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar dan kekayaan nasional terkonsentrasi di kalangan segelintir elit. Deforestasi dan polusi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada eksploitasi alam, sementara kebijakan mitigasi iklim masih setengah hati.
Di usianya yang menginjak 80 tahun, Indonesia harus bertanya pada diri sendiri ke mana arahnya. Ini adalah upaya kolektif yang membutuhkan keberanian untuk bertindak melawan kepentingan sempit. Kita membutuhkan pemimpin dengan kemauan politik dan keberanian untuk memulihkan etika publik dan kebijakan yang mengutamakan rakyat daripada oligarki.
Negara harus didirikan berdasarkan moralitas, bukan sekadar retorika. Seperti yang dikatakan Sukarno pada 1 Juni 1945, Pancasila harus menjadi "bintang penuntun" bangsa, atau kompas moral. Mohammad Hatta menekankan bahwa kemerdekaan tanpa integritas menyebabkan kekacauan moral, dan Tan Malaka berpendapat bahwa "kebebasan tanpa kebenaran adalah omong kosong; kekuasaan tanpa moralitas adalah kejahatan".
Pemerintahan Prabowo harus memilih antara melanjutkan pola kompromi yang lama dan memulai perombakan menyeluruh.
Solusi bagi kompas moral yang hilang membutuhkan pendekatan bercabang tiga. Pertama, pulihkan nilai-nilai dasar Pancasila melalui reorientasi pendidikan dan budaya politik. Kedua, laksanakan reformasi kelembagaan dan penegakan hukum secara menyeluruh untuk memulihkan kredibilitas lembaga seperti KPK dan Polri. Ketiga, dorong perubahan ekonomi yang berkeadilan dengan mengakhiri kebijakan yang hanya menguntungkan kaum elit.
Hilangnya kompas moral Indonesia bukan hanya menyangkut moralitas individu, tetapi juga arah seluruh bangsa. Solusinya membutuhkan ketulusan para pemimpin, tekanan publik yang konsisten, dan perubahan fundamental terhadap nilai-nilai bangsa. 
Artikel ini adalah terjemahan dari artikel yang telah diterbitkan di Jakarta Post.