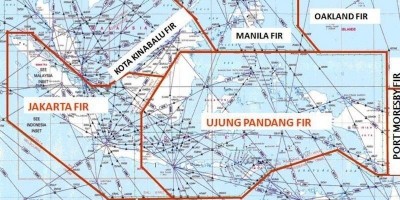Oleh: Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS)
PADA 21 Juli, Presiden Prabowo Soebianto meresmikan 80.000 koperasi di 80.000 desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebuah langkah yang dipandang sebagai bagian dari upaya mengembalikan perekonomian ke arah konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan dalam bukunya, Paradoks Indonesia.
Pemerintah juga mengumumkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) akan menerima pinjaman lunak dari bank-bank BUMN dan bank pembangunan daerah (BPD). Potensi penyaluran kredit dapat mencapai Rp 240 triliun (US$15 miliar), atau sekitar 10% dari total APBN 2025.
Di atas kertas, ini merupakan langkah strategis untuk mendorong perekonomian rakyat dengan memperluas basis usaha mikro dan kecil. Diharapkan dengan bantuan ini, koperasi desa mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri melalui sistem produksi dan distribusi yang dikuasai oleh rakyat.
Tentu saja, gagasan dan cita-cita luhur ini harus didukung oleh masyarakat pedesaan, yang selama ini telah lama terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Namun, ini tidak berarti kita harus mengabaikan pengalaman pahit koperasi di masa lalu.
Banyak kritik terhadap mentalitas top-down yang sering kali menyebabkan kegagalan berbagai program populis yang memiliki "niat baik", tetapi tidak dirancang dengan akal sehat dan pengalaman lapangan.
Literatur tentang koperasi di berbagai negara tidak menyajikan kisah sukses koperasi yang didirikan pemerintah. Banyak negara telah mencoba pendekatan "desain besar top-down" untuk mengembangkan ekonomi rakyat, yang pada akhirnya menyebabkan korupsi, pemborosan anggaran, dan kegagalan jangka panjang.
Uganda dan India memberikan pelajaran berharga bagaimana gerakan koperasi top-down menjadi sarang korupsi di kalangan pejabat lokal dan elit politik, dan kemudian runtuh karena kurangnya transparansi dan dukungan terhadap kebutuhan riil.
Mungkin Prabowo masih percaya bahwa koperasi adalah takdir Indonesia, dan harus dikejar dengan tekun, meskipun mereka telah gagal menjadi pilar ekonomi nasional. Tidak seperti di Uganda, Venezuela, atau India, konstitusi kita dengan jelas menetapkan bahwa ekonomi nasional disusun sebagai usaha patungan berdasarkan asas kekeluargaan.
Inisiatif KDMP menuntut pengawasan publik terhadap potensi bahaya implementasi yang tidak memiliki ekosistem, transparansi, dan akuntabilitas.
Pertama, budaya koperasi. Budaya yang baik akan membawa kesuksesan, dan kesuksesan akan menciptakan budaya baru. Pembentukan koperasi sejatinya didasarkan pada empat syarat utama: kebutuhan, kesadaran, rasa saling percaya, dan partisipasi anggota.
Semua syarat dasar ini akan memampukan anggota koperasi memiliki pemahaman yang luas tentang koperasi dan mentalitas yang kuat dan jujur dalam menjalankan koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam ekosistem koperasi, termasuk kekuatan modal di luar koperasi yang mengendalikan jalur produksi dan distribusi. Tanpa budaya koperasi yang telah terbentuk sebelumnya, sulit bagi anggota koperasi yang berorientasi ke atas untuk mengembangkan komitmen dan integritas guna berpartisipasi secara konsisten dalam kegiatan dan menjadikan koperasi sebagai satu-satunya sarana ketahanan ekonomi mereka.
Kedua, potensi kredit macet. Jika seluruh 80.000 koperasi diberikan pinjaman lunak setara Rp 3 miliar tanpa mekanisme kredit yang berbasis kelayakan, kemungkinan besar akan berubah menjadi krisis kredit macet nasional. Alih-alih menciptakan koperasi mandiri, kita justru akan menciptakan jaringan utang rakyat kepada negara.
Kita memiliki rekam jejak yang buruk terkait penyaluran pinjaman lunak ke pedesaan, melalui koperasi, kewirausahaan, dan mekanisme pemerintahan desa.
Program Kredit Usaha Tani (KUT) pada tahun 1995-2000 mencapai Rp10 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya sangat rendah, antara 32 dan 35 persen. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 mengungkap penyelewengan dana dan pembukuan fiktif di lebih dari 30 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diaudit. Banyak BUMDes yang gagal karena mentalitas proyek, bukan mentalitas kewirausahaan, dan Presiden Prabowo Subianto akhirnya menandatangani peraturan pemerintah untuk menghapuskan utang macet senilai Rp 8 triliun yang menjadi beban petani dan UMKM.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan 851 kasus korupsi terkait desa dari tahun 2015 hingga 2022 yang melibatkan 973 tersangka, dengan kepala desa menjadi separuh pelaku. Penyebab utama kasus-kasus ini adalah tingginya biaya politik bagi kepala desa dan lemahnya pengawasan.
Ketiga, kepentingan politik elektoral. Jika pendekatan top-down terhadap pembentukan koperasi tidak didorong oleh pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini dapat menjadi alat bagi elit untuk mendistribusikan proyek dan melanggengkan kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan sebelumnya, kepala desa dimobilisasi untuk mendukung potensi masa jabatan ketiga Joko “Jokowi” Widodo dengan menggunakan dana desa dan perpanjangan masa jabatan sebagai iming-iming.
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan koperasi Merah Putih. Dengan meningkatnya penyaluran dana ke desa, mencapai Rp 2 miliar dana desa dan Rp 3 miliar dana Koperasi Merah Putih, dari sisi politik, jumlah dana ini memberikan daya ungkit yang signifikan bagi pemerintah pusat untuk memobilisasi desa sebagai kekuatan politik nyata guna mendukung upaya Presiden Prabowo untuk periode kedua. Korupsi dana desa oleh kepala desa dapat menyandera koperasi dan mengarahkan mereka untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan di semua tingkatan.
Meskipun pengurus koperasi bukan pegawai negeri sipil (ASN), dan dana koperasi tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyalahgunaan dana koperasi tetap dapat dianggap sebagai korupsi karena pinjaman dari bank BUMN dan BPD merupakan aset publik. Pengurus koperasi seharusnya belajar dari kasus Sritex.
Program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi warisan penting bagi Prabowo jika dikawal oleh transparansi dan ekosistem usaha berbasis komunitas. Namun, jika dijalankan secara tergesa-gesa dengan motivasi populis dan politis menjelang tahun 2029, program ini hanya akan menjadi versi baru dari koperasi yang mandek di era reformasi.
Yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Jika kepercayaan itu kembali dirusak, kita tidak hanya akan menghadapi utang macet tetapi juga krisis legitimasi bagi ekonomi kerakyatan.
Sebagaimana digariskan oleh Mohammad Hatta, "Bapak Koperasi Indonesia", koperasi bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga moral yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas.
Sulit untuk menepis kecurigaan bahwa pembentukan KDMP terutama dimotivasi oleh iming-iming pinjaman lunak miliaran rupiah. Kurangnya partisi anggota pada akhirnya menyebabkan penggunan modal dan aset koperasi tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Ribuan koperasi desa mungkin dapat terbentuk dalam satu hari, tetapi budaya koperasi tidak dapat dimobilisasi dengan keputusan (SK) dan anggaran. Budaya koperasi tumbuh melalui pengalaman kolektif dalam hubungan sosial yang egaliter.
Pertanyaan utamanya adalah, mengapa kita tidak berfokus pada koperasi yang telah terbukti tangguh? Ribuan koperasi primer di sektor simpan-pinjam, pertanian, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berjuang untuk mengakses modal, digitalisasi dan pasar.
Mereka tidak membutuhkan janji, tetapi akses ke kredit yang terjangkau, insentif pajak, pelatihan digital, dan integrasi ke dalam ekosistem e-commerce. Mereka juga membutuhkan kontak langsung dengan pasar melalui pameran yang diselenggarakan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. 
Artikel ini terjemahan dari artikel pada The Jakarta Post.