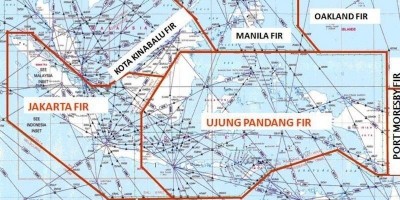Oleh: Moh Samsul Arifin, Pemerhati Demokrasi
INI bukan cerita fiksi yang menyelinap dalam politik. Tapi politik faktual yang mirip-mirip fiksi. Titik baliknya adalah akomodasi Koalisi Indonesia Maju terhadap partai politik nonpendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekian bulan sebelum pilkada serentak, November 2024.
Nasdem, PKS dan PKB tiba-tiba berubah haluan. Alih-alih mengumumkan diri sebagai barisan parpol yang akan beroposisi di DPR, tiga serangkai itu malah mendukung lawan mereka di Pilpres 2024. Sebagian partai ini malah mengirim kader mereka ke kabinet Merah Putih. Terakhir, Nasdem menyatakan sekali lagi mendukung pemerintahan Prabowo lewat rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan (8 Agustus 2025). Kali ini ditambah diksi 'sepenuh hati'.
Kisah ganti haluan tiga partai ini menjelaskan bahwa partai politik di negeri kita cuma siap berkuasa atau berada di eksekutif. Padahal fatsunnya mereka berada di luar orbit kekuasaan eksekutif (government). Ada 40,97 juta pemilih atau setara 24,9 suara sah yang memilih Anies-Muhaimin. Di antara 40,97 juta pemilih ini pasti ada juga yang memilih Nasdem, PKS dan PKB di pemilu legislatif.
Suara 40,97 juta itu jika diartikulasikan dengan kalimat jelas berarti emoh dipimpin Prabowo-Gibran. Demikian juga 27,04 juta suara yang mencoblos Ganjar-Mahfud, tidak sedang menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran.
Begitulah kenyataannya. Logika awam tak senafas dengan logika elite partai. Di mana urgensi pemilu jika 'ujung bin akhir' dari kisah persaingan dalam pemilu bermuara pada seluruh parpol masuk pemerintahan dan berhak atas kursi di kabinet?
Kisah ini bukan fenomena gres. Partai Golkar melakukannya di tahun 2004 ketika tampuk kepemimpinan beralih dari Akbar Tandjung ke Jusuf Kalla. Gerindra tahun 2019. Juga PAN yang dikemudikan Zulkifli Hasan. Dan paling anyar, Partai Demokrat bergabung ke kabinet Joko Widodo pada Februari 2024, setelah sembilan tahun di luar pemerintahan.
Dalam teori pemisahan kekuasaan dikenal Trias Pilitica, dalam bahasa Yunani berarti politik tiga serangkai. Konsep ini ingin mencegah kekuasaan negara yang absolut. Berhulu pada John Locke, konsep ini dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755).
Di negeri kita ada tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari sana telah terang benderang: Berkuasa itu tak selalu harus berada di goverment.
DPR sebagai legislator secara langsung sesungguhnya punya fungsi checks and balances terhadap eksekutif. Cuma dalam praktik tidak selalu dijalankan karena parpol-parpol pemilik kursi di DPR menyokong pemerintah, tergabung dalam koalisi pemerintahan. Kita bisa cek ini sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo atau Abdurrahman Wahid dan Megawati. Lubangnya MK sebagai kekuasaan kehakiman pernah menyatakan mereja tak perlu diawasi --dalam term checks and balances itu. Sedangkan Mahkamah Agung diawasi oleh Komisi Yudisial.
Karena fungsi checks and balances tadi tidak inheren dijalankan parpol pemilik kursi di DPR, kita butuh institusionalisasi atau pelembagaan oposisi. Harus ada parpol, berapa pun jumlahnya, yang mengumumkan diri sebagai oposan. Dengan deklarasi itu, publik bisa menagih kepada parpol yg bersangkutan, jika tak menjalankan fungsi checks and balances itu.
Setelah Nasdem, PKS dan PKB emoh berada di luar pemerintah atau mendukung pemerintah, harapan publik tersisa kepada PDI-Perjuangan.
Namun, harapan tinggal harapan. Dalam kongres yang dilakukan secara tertutup di Bali, publik patah hati. Partai yang memiliki DNA oposisi ini justru bergerak menjadi partai "bukan-bukan". Tidak oposisi, tidak juga koalisi.
Dalam pidato politik di penutupan Kongres di Bali, Megawati yang kembali didapuk menjadi ketua umum menegaskan, "Sistem presidensial seperti yang kita anut tak kenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan".
Dalam praktik konkret, apakah yang dilakukan PDI-P di sepuluh tahun SBY bukan oposisi? Di antara 2004-2014, PDI-P perbah menolak kenaikan harga BBM. Itu sikap yang bertolak belakang dengan pemerintah. Kritik dan suara lain itu amat dibutuhkan oleh publik, sebab eksekutif belum tentu benar atau correct dalam merancang dan memutuskan kebijakan. Penguasa tak selalu benar dan karena itu wajib dikontrol.
Sebelum Kongres VI di Bali, PDIP yang masih abu-abu, tidak menyatakan sebagai oposan. Tapi, di sebagian kecil isu, PDI-P tetap kritis. Contohnya dalam isu "penulisan ulang sejarah" yang digawangi Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Setelah negeri kita menganut kembali multipartai di Pemilu 1999, tidak gampang membentuk pemerintahan yang kuat sekaligus melembagakan oposisi. Presiden terpilih harus memperhatikan parpol penyokongnya di DPR. Jika kekuatan koalisi pendukungnya di Pilpres kurang dari 50 persen, itu mendorongnya untuk mencari kursi tambahan pada parpol lain yang di masa Pilpres adalah seterunya. Inilah yang belum terselesaikan sejak 2004, 2014 dan 2024.
Masalahnya, presiden terpilih acap kali tergoda mengajak sebanyak mungkin parpol masuk dalam pemerintahannya. Bahkan saat kursi pendukungnya, yakni 50 persen plus satu di DPR, telah terpenuhi. Ini dia yang membuat fungsi balance of power DPR tak berjalan.
Saat ini, dengan dukungan 100 persen parpol di DPR, siapa yang akan mengontrol pemerintah? Seandainya pun PDI-P akan bersikap lantang dan tegas di DPR, publik tak punya kepastian di isu atau topik apa itu akan dilakukan? Adakah ini 'kutukan' sistem pemerintahan presidensialisme dengan basis multipartai?