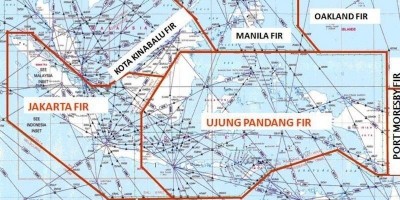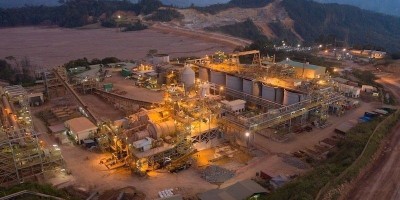Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta
PER Mei 2025, Bank Indonesia (BI) mencatatkan penurunan cadangan devisa sebesar USD 4,6 miliar dibandingkan posisi bulan sebelumnya.
Secara nominal, angka ini setara dengan lebih dari Rp80 triliun—jumlah yang bahkan sebanding dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas fiskal nasional tahun ini.
Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal serius yang menunjukkan tekanan terhadap fondasi makroekonomi Indonesia yang harus direspons secara strategis dan mendalam oleh otoritas moneter.
Sebagai benteng pertahanan utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan persepsi pelaku pasar terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi nasional, cadangan devisa yang menurun dalam jumlah signifikan patut dikhawatirkan.
Cadangan devisa bukan hanya angka di atas kertas, melainkan simbol kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia dan alat intervensi riil bagi stabilitas eksternal.
Ada tiga alasan mengapa penurunan sebesar USD 4,6 miliar ini tidak bisa dianggap remeh.
Pertama, dalam konteks global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan suku bunga tinggi The Fed masih mendominasi sentimen pasar keuangan.
Kedua, dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah mendorong intervensi agresif BI di pasar valas, yang berkontribusi besar terhadap penurunan cadangan devisa. Ketiga, besarnya repatriasi dividen dan pembayaran utang swasta yang jatuh tempo pada kuartal kedua turut menekan posisi devisa.
Namun pertanyaannya, apakah kondisi ini tak terhindarkan? Atau justru mencerminkan kurangnya ketahanan sistem moneter kita terhadap gejolak eksternal dan tekanan struktural dalam negeri?
Menurut hemat saya, inilah momentum yang tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan introspeksi kebijakan dan memperkuat empat pilar ketahanan devisa secara sistemik.
Pertama, penguatan manajemen ekspektasi nilai tukar. Sejauh ini, intervensi BI di pasar valas tampak reaktif terhadap gejolak nilai tukar harian.
Namun volatilitas jangka pendek seharusnya tidak menjadi justifikasi bagi pengurasan cadangan devisa yang agresif. Diperlukan strategi forward guidance yang lebih komunikatif, disertai transparansi arah kebijakan suku bunga dan intervensi pasar.
BI harus bisa menanamkan kepercayaan pelaku pasar bahwa stabilitas nilai tukar tidak selalu identik dengan pertahanan di harga nominal tertentu, melainkan pada pengelolaan ekspektasi yang kredibel.
Kedua, diversifikasi instrumen pembentukan devisa. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan aliran modal portofolio jangka pendek menjadikan cadangan devisa kita sangat rentan terhadap volatilitas global.
Sudah saatnya BI bersama otoritas fiskal menyusun strategi jangka menengah untuk memperluas basis penerimaan devisa melalui ekspor jasa (seperti pariwisata medis dan digital), promosi investasi langsung yang menciptakan ekspor berkelanjutan, serta kebijakan local content yang mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku.
Di sini, sinergi antara BI dan Kementerian Perdagangan, Kemenperin, serta BKPM menjadi sangat krusial.
Ketiga, reformasi pasar valas domestik. Tingginya permintaan valas dari sektor korporasi dan rendahnya pasokan dolar di pasar spot dalam negeri menunjukkan bahwa pasar valas Indonesia belum cukup dalam dan efisien.
BI perlu mendorong penguatan pasar valas domestik melalui instrumen hedging yang lebih mudah diakses, pelonggaran kebijakan rekening valas dalam negeri, serta insentif bagi repatriasi devisa ekspor (DHE) yang lebih kompetitif.
Kebijakan DHE selama ini belum cukup efektif karena terlalu menekankan pendekatan administratif ketimbang menciptakan ekosistem yang menarik bagi eksportir untuk menyimpan devisa mereka di dalam negeri.
Keempat, perlunya rekalibrasi kebijakan suku bunga.
Dalam konteks dual mandate—menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar—BI harus mempertimbangkan dengan hati-hati trade-off antara suku bunga tinggi untuk menarik modal asing dan risiko terhadap pertumbuhan kredit domestik.
Kenaikan suku bunga acapkali menjadi respons utama terhadap tekanan nilai tukar, namun tanpa koordinasi dengan kebijakan fiskal dan struktur pasar keuangan, kebijakan ini bisa berujung pada stagnasi ekonomi yang kontraproduktif. Oleh karena itu, BI perlu menyeimbangkan antara daya tarik aset rupiah dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi domestik.
Kita tidak boleh lupa bahwa posisi cadangan devisa per April 2025 yang tercatat sebesar USD 136,2 miliar kini telah menyusut drastis ke kisaran USD 131,6 miliar.
Penurunan sebesar ini hanya dalam satu bulan menunjukkan tekanan yang luar biasa.
Jika tren ini tidak dibendung, dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menghadapi krisis kepercayaan yang jauh lebih sulit dikendalikan—terutama menjelang semester kedua tahun ini di mana volatilitas global biasanya meningkat.
Namun, ini bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia semata.
Pemerintah pusat harus turut memperkuat sisi fundamental fiskal dengan menjaga defisit anggaran dalam batas wajar, mempercepat belanja produktif yang mendorong substitusi impor, serta menata ulang strategi utang luar negeri yang bisa membebani devisa.
Dalam jangka menengah, reformasi struktural yang mendalam—seperti hilirisasi industri yang benar-benar berorientasi ekspor, bukan sekadar pemrosesan bahan mentah—harus menjadi fokus utama pembangunan ekonomi nasional.
Pada akhirnya, pelemahan cadangan devisa sebesar USD 4,6 miliar ini bukan hanya isu teknis neraca pembayaran, tetapi refleksi dari lemahnya koordinasi antar kebijakan ekonomi dan kegagalan menciptakan ekosistem devisa yang resilien.
Bank Indonesia memiliki peran sentral sebagai otoritas moneter, tetapi tanpa sinergi yang erat dengan kementerian teknis dan pelaku usaha, ketahanan devisa akan selalu rapuh di tengah gelombang eksternal.
Sudah saatnya kita bergerak dari sekadar respons jangka pendek menuju reformasi kebijakan devisa yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis data.
Jangan sampai setiap tahun kita hanya bisa menyalahkan sentimen global, sementara keroposnya fondasi devisa kita justru berasal dari dalam negeri.
Indonesia butuh Bank Sentral yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi arsitek strategi devisa nasional. Momentum ini harus dimanfaatkan. Jika tidak, kita hanya akan mengulang siklus intervensi, penurunan cadangan, lalu kembali mencari kambing hitam.