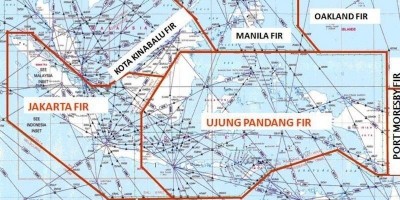Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
AMERIKA Serikat (AS) kembali menyoroti kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (National Payment Gateway), melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
Kritik utama AS berkisar pada ketidakikutsertaan perusahaan asing, terutama dari Negeri Paman Sam, dalam proses pengembangan kebijakan tersebut.
Namun, di balik protes AS, Indonesia memiliki alasan kuat untuk mempertahankan QRIS sebagai bagian dari strategi kedaulatan ekonomi, keamanan data, dan inklusi keuangan.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menilai bahwa Indonesia cenderung menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku industri internasional, terutama dari Negeri Paman Sam.
Isu ini bukan hanya soal tata kelola regulasi, tapi menyentuh isu strategis yang lebih dalam: kedaulatan ekonomi, keamanan data, efisiensi biaya, dan inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
]Pertanyaan besarnya: bagaimana negara berkembang seperti Indonesia bisa menjaga kepentingan nasionalnya di tengah tekanan globalisasi yang kerap didominasi kepentingan korporasi multinasional?
QRIS: Bukan Sekadar Alat Pembayaran, Tapi Pilar Kedaulatan Digital
QRIS telah menjadi tulang punggung transaksi digital di Indonesia, dengan lebih dari jutaan merchant dan ratusan juta pengguna aktif pada 2025.
QRIS bukan sekadar teknologi pembayaran berbasis kode QR. Ia adalah infrastruktur publik digital yang menyatukan berbagai metode pembayaran elektronik agar kompatibel secara nasional.
Tujuan Bank Indonesia menerapkan standar ini adalah untuk menyederhanakan sistem pembayaran, menurunkan biaya transaksi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal ke seluruh pelosok negeri.
Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana inklusi keuangan menjadi tantangan utama, QRIS telah menjadi salah satu katalis penting dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang sejak 2019 memastikan seluruh transaksi QR code mengikuti standar nasional.
Tujuannya jelas: menyatukan fragmentasi sistem pembayaran digital, menekan biaya transaksi, dan memperluas akses keuangan bagi UMKM serta masyarakat pedesaan.
Namun, AS melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang menghambat integrasi dengan sistem global.
Bagi Indonesia, QRIS bukan sekadar alat transaksi, melainkan instrumen strategis untuk melindungi data finansial warganya.
Dengan maraknya ancaman cybercrime dan potensi penyalahgunaan data oleh korporasi asing, kontrol penuh atas infrastruktur pembayaran adalah langkah defensif yang rasional.
Bayangkan jika sistem QRIS dioperasikan oleh perusahaan asing: data transaksi ratusan juta orang Indonesia bisa terekam di server luar negeri, rentan terhadap pengawasan pemerintah asing atau kebocoran yang merugikan konsumen.
Proteksionisme atau Perlindungan? Memahami Kebijakan Kepemilikan Asing
AS juga mengkritik pembatasan kepemilikan asing di sektor pembayaran, seperti batas 20% kepemilikan untuk perusahaan infrastruktur backend.
Kebijakan ini dinilai menghambat investasi asing. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan regulasi serupa. India, misalnya, membatasi kepemilikan asing di perusahaan fintech hingga 49% untuk melindungi pasar domestik.
China bahkan menutup rapat sistem pembayaran digitalnya dengan kebijakan “Great Firewall”.
Pembatasan ini bukan tanpa alasan. Sektor keuangan adalah urat nadi ekonomi suatu negara.
Jika dikuasai asing, bukan hanya data yang rentan, tetapi stabilitas moneter dan kebijakan fiskal bisa dipengaruhi oleh kepentingan luar.
Krisis keuangan Asia 1998 menjadi bukti betapa liberalisasi sektor finansial yang tak terkendali bisa berujung pada kehancuran ekonomi.
Dengan membatasi kepemilikan asing, Indonesia berusaha memastikan bahwa keputusan strategis di sektor pembayaran tetap di tangan lokal, sehingga respons terhadap krisis bisa lebih cepat dan terukur.
Efisiensi Biaya dan Inklusi Keuangan
Di luar isu geopolitik dan kedaulatan, pembangunan sistem pembayaran domestik juga sangat rasional dari sisi efisiensi biaya.
Sebelum GPN dan QRIS, transaksi yang menggunakan jaringan internasional sering kali dikenakan biaya tinggi karena harus melalui switching luar negeri.
Ini bukan hanya memberatkan konsumen, tapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini menjadi tulang punggung perekonomian.
Dengan QRIS, biaya transaksi bisa ditekan, sehingga makin banyak pelaku usaha informal yang dapat bergabung ke dalam ekosistem keuangan digital.
Ini juga berdampak positif bagi pemerintah dalam hal perluasan basis pajak dan distribusi bantuan sosial secara digital. Efisiensi ini bukan hanya soal keuntungan komersial, tapi menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Agenda Nasional: Kemandirian Sistem Pembayaran
Kritik AS terhadap GPN—yang mewajibkan transaksi kartu debit/kredit diproses melalui gateway lokal—juga perlu dilihat dari perspektif sejarah.
Sebelum GPN, sekitar 90% transaksi kartu di Indonesia dikuasai jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard, dengan biaya switching yang tinggi.
GPN hadir untuk menekan biaya tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem luar.
Langkah ini sejalan dengan tren global. Rusia, misalnya, mengembangkan sistem Mir Card setelah sanksi Barat memutus aksesnya ke SWIFT.
Namun, AS menganggap GPN dan QRIS “tidak kompatibel” dengan sistem global.
Di sini terjadi paradoks: di satu sisi, perusahaan AS ingin integrasi, tetapi di sisi lain, mereka enggan menyesuaikan diri dengan standar lokal.
Padahal, kompatibilitas seharusnya bersifat dua arah. Alih-alih memaksa Indonesia mengadopsi standar global, perusahaan asing bisa berinovasi agar layanannya selaras dengan QRIS.
Justru ketidakmampuan beradaptasi dengan kebijakan lokal yang menjadi akar masalah.
Ketegangan Globalisasi vs. Nasionalisme Ekonomi
Kritik AS terhadap QRIS dan GPN mencerminkan ketegangan abadi antara globalisasi dan nasionalisme ekonomi.
Bagi AS—yang rumah bagi raksasa fintech seperti PayPal, Stripe, dan Visa—kebijakan Indonesia dianggap menghambat ekspansi bisnis mereka.
Namun, Indonesia harus memprioritaskan kepentingan 277 juta warganya.
Liberalisasi sektor pembayaran tanpa filter bisa mematikan startup fintech lokal yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional.
Contohnya, di Afrika, dominasi M-Pesa (meski sukses meningkatkan inklusi keuangan) justru mempersempit ruang bagi pengembang lokal untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual.
Selain itu, tuntutan AS agar BI "lebih transparan" dalam penyusunan kebijakan perlu dikritisi.
Setiap negara berdaulat berhak merumuskan regulasi sesuai kebutuhan nasionalnya tanpa intervensi asing.
Protes AS mirip dengan reaksi mereka terhadap kebijakan data lokal (data localization) di Uni Eropa melalui GDPR.
Jika Indonesia menyerah pada tekanan ini, bisa jadi ini menjadi preseden buruk di mana kebijakan publik ditentukan oleh lobi korporasi, bukan kepentingan rakyat.
Menuju Solusi Simbiosis: Bagaimana Strategi Negosiasi Seharusnya?
Meski kedaulatan ekonomi adalah hak mutlak Indonesia, dialog konstruktif dengan pemain global tetap diperlukan.
Tudingan bahwa kebijakan Indonesia bersifat protektif sebetulnya merupakan bentuk proyeksi dari kekhawatiran korporasi global terhadap potensi kehilangan pangsa pasar.
Tapi proteksi dalam arti melindungi kedaulatan sistem keuangan nasional adalah hal yang wajar, dan bahkan wajib dilakukan oleh negara manapun yang serius membangun kemandirian ekonominya.
Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan kerja sama internasional.
Namun, keterbukaan itu harus diletakkan dalam kerangka yang tidak mengorbankan kepentingan nasional jangka panjang.
Ketika BI menetapkan bahwa lembaga switching GPN harus berbasis di dalam negeri dan memiliki lisensi lokal, itu adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan kontrol dan transparansi dalam pengelolaan sistem pembayaran domestik. ini harus dipertahanakan karena terkait kepentingan nasional.
Perusahaan asing tetap bisa berpartisipasi, namun harus melalui kemitraan strategis dengan entitas lokal dan mendukung transfer teknologi. Ini adalah mekanisme yang adil dan berorientasi pada penguatan kapasitas dalam negeri, bukan semata-mata eksklusivitas.
Berikut hal yang bisa dilakukan oleh BI dan Pemerintah dalam negosiasai soal QRIS dengan AS:
Pertama, BI bisa membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan.
Misalnya, mengizinkan partisipasi asing dalam pengembangan teknologi QRIS dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bahwa QRIS bukan hambatan, tetapi peluang kolaborasi.
Standar QRIS bisa dipromosikan sebagai model bagi negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengannya.
Ketiga, Indonesia bisa mengadopsi pendekatan “interoperabilitas bertahap”.
Misalnya, memastikan QRIS kompatibel dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) atau PromptPay (Thailand) terlebih dahulu, sebelum melangkah ke integrasi global.
Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Jangan Negosiasi Soal Kedaulatan Digital
QRIS dan GPN adalah representasi dari semangat Indonesia untuk membangun sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan berdaulat.
Kritik dari AS adalah hal yang wajar dalam dinamika perdagangan global, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk mundur dari agenda nasional.
Justru, inisiatif ini harus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pemain utama dalam ekonomi digital global.
Menyerahkan kontrol QRIS kepada pihak luar negeri adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan ekonomi dan keamanan data rakyat.
Maka, di sinilah kita harus berdiri tegak: menjaga kemandirian dengan tetap menjalin kerja sama yang adil dan berimbang.