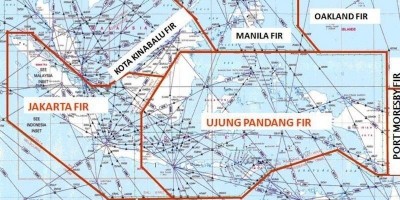Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
MARI memulai dari fakta yang belakangan menjadi bahan perbincangan nasional: wacana pengambilalihan 51% saham sebuah bank swasta terbesar—BCA—oleh negara kembali mengemuka.
Argumen pro di ruang publik bertolak dari memori krisis 1998, dari beban rekapitalisasi dan jejak BLBI, sementara pihak yang menolak menilai langkah seperti itu akan menggerus kepastian hukum dan iklim investasi.
Dari Wacana 51% hingga Kekhawatiran Kepastian Hukum
Bahkan sempat muncul klaim bahwa pengambilalihan akan menambah ruang fiskal lembaga investasi negara, namun pihak bank dan lembaga dimaksud menyatakan tidak ada rencana akuisisi.
Di tengah silang pendapat itu, pelaku pasar mewaspadai potensi gejolak persepsi, sementara publik mempertanyakan makna keadilan setelah dua dekade lebih negara menanggung biaya penyelamatan sistem.
Pertanyaan yang lebih jernih lalu muncul: apakah setiap gagasan koreksi pasti identik dengan “pengambilalihan paksa” dan kekacauan pasar, ataukah masih ada jalan yang sahih, terukur, dan pro-pasar untuk menata ulang relasi negara dengan sektor keuangan strategis?
Pertanyaan Kunci: Apakah Intervensi Selalu Buruk bagi Pasar?
Negara boleh bertindak korektif tanpa membuat pasar panik; yang dibenci pasar adalah ketidakpastian, bukan kebijakan yang jelas.
Kecurigaan terhadap intervensi negara sering berangkat dari trauma masa lalu: begitu negara menyentuh kepemilikan, pasar ditakuti akan lari.
Tetapi pasar sebenarnya tidak alergi terhadap tindakan pemerintah; yang ditolak pasar adalah ketidakpastian.
Selama kerangka hukumnya jelas, kompensasi kepada pemegang saham wajar, mandatnya terbatas, dan komunikasi kebijakannya konsisten, langkah korektif justru dibaca sebagai pengurangan risiko sistemik, bukan penambahan risiko politik.
Dengan kata lain, inti persoalan kita bukan “apakah negara boleh bertindak”, melainkan “bagaimana negara bertindak”—dan bagaimana memastikan tindakannya memperkuat keadilan fiskal tanpa meruntuhkan kepercayaan investor.
Ongkos Publik, Surplus Privat, dan Risiko Moral
Krisis 1998 memaksa negara membangun “jembatan darurat” agar sistem perbankan tidak runtuh.
Biayanya raksasa, ditanggung publik, dan saat itu merupakan pilihan yang tak terhindarkan.
Dua puluh tahun lebih berlalu, beberapa institusi yang dulu ditopang negara tumbuh dominan dan sangat menguntungkan.
Di sinilah problem kebijakan publik mengeras: ketika ongkos ditanggung rakyat, tetapi surplus pascakrisis terkonsentrasi pada segelintir privat, muncul risiko moral hazard yang menembus generasi.
“Move on” dari krisis tidak berarti menutup buku tanpa koreksi; “move on” berarti menyelaraskan akibat agar rasa keadilan sosial tidak kering.
Maka yang kita butuhkan bukan peninjauan kembali transaksi lama, melainkan desain kebijakan ke depan yang menangkap sebagian nilai sistemik bagi publik tanpa mematikan insentif swasta.
Gagasan Korektif: Prospektif, Berbasis Hukum, dan Terukur
Ada tiga gagasan yang, menurut saya, memenuhi syarat keadilan sekaligus diterima logika pasar.
Pertama, kontribusi stabilitas atau bank levy, dipungut secara prospektif berdasarkan ukuran liabilitas dan profil risiko.
Ini bukan penagihan “utang lama”, melainkan premi wajar atas status sistemik yang membawa subsidi implisit—akses dana murah, kepercayaan publik, dan dukungan lender of last resort.
Kedua, hak emas (golden share) untuk bank yang betul-betul sistemik.
Hak ini bukan nasionalisasi, melainkan kunci veto terbatas bagi keputusan korporasi yang dapat mengganggu sistem pembayaran dan kesehatan intermediasi.
Ketiga, bila opsi kepemilikan dipilih, lakukan akuisisi terukur dengan kompensasi wajar dan sertakan peta jalan keluar yang mengikat: negara masuk untuk tujuan yang jelas, dan wajib keluar ketika tujuan tercapai.
Tiga instrumen ini berdiri di atas undang-undang yang terang, tata kelola yang profesional, dan komunikasi kebijakan yang konsisten.
Analogi Bendungan
Bayangkan krisis sebagai banjir besar dan kebijakan rekap sebagai bendungan yang menyelamatkan kota.
Setelah air surut, sungai kembali mengalir, tetapi tidak semua sawah kebagian air secara adil. Menambah pintu air, memasang katup tekanan, atau mengarahkan sebagian aliran ke kanal publik bukanlah tindakan merusak sungai; itu tata kelola air modern.
Begitu pula dengan sektor perbankan: penataan ulang bukan berarti menutup pasar, melainkan mengelola arus nilai agar manfaat stabilitas yang dulu didanai rakyat kembali mengalir ke publik, tanpa memutus insentif bagi swasta untuk berinovasi dan bersaing.
Analogi ini membantu kita melihat esensi kebijakan: negara bukan hendak menutup keran, melainkan menyeimbangkan tekanannya.
Menyederhanakan Teknis: Dampaknya bagi Investor, Nasabah, dan Negara
Bagi investor, kepastian adalah mata uang utama. Jika koridor hukum tentang siapa yang sistemik, bagaimana dasar pengenaan levy, kapan golden share dapat diaktifkan, serta seperti apa peta jalan keluar kepemilikan ditulis gamblang, risiko dapat dihitung dan valuasi menyesuaikan secara rasional.
Bagi nasabah, penataan ini berarti layanan yang lebih aman dan efisien, karena keputusan strategis bank dijaga agar selaras dengan kepentingan sistem pembayaran dan inklusi keuangan.
Bagi negara, kebijakan ini memperkuat daya tahan makro melalui dana penyangga krisis yang lebih stabil, hak kendali minimal atas keputusan yang berdampak sistemik, dan kepastian bahwa subsidi implisit kebijakan tidak kembali membentuk rente privat semi-permanen.
Menjawab Keberatan: Tender Krisis, “Kotak Pandora”, dan Kepastian Hukum
Ada yang menilai tender masa krisis sudah sahih dan transparan, sehingga perkara dianggap selesai.
Legalitas masa lalu tidak saya perdebatkan; yang saya pertanyakan adalah apakah hasil akhirnya telah selaras dengan keadilan antargenerasi.
Pasar krisis bersifat tipis, premi risiko tinggi, dan akses pembiayaan terbatas—struktur seperti ini wajar menghasilkan harga diskon dalam dan surplus jangka panjang untuk pemenang.
Koreksi ke depan melalui levy atau golden share bukan pembatalan tender, melainkan penyeimbang hasil akhir agar manfaat stabilitas tidak terkunci pada privat.
Ada pula kekhawatiran bahwa membahas akuisisi akan membuka “kotak pandora” dan memicu gugatan terhadap seluruh transaksi lama.
Di sinilah presisi desain memainkan peran: ruang lingkup dapat dibatasi pada bank yang jelas-jelas sistemik, tujuan dibatasi pada indikator terukur seperti pendalaman kredit produktif, efisiensi layanan, dan perluasan inklusi, serta diberi sunset clause yang memaksa negara melepas kembali kontrol ketika sasaran tercapai.
Dengan pendekatan ini, kepastian hukum justru menguat: tujuan jelas, ukuran terdefinisi, dan garis akhirnya tegas.
Usulan Desain Implementasi: Jalur Hukum, Kompensasi Wajar, Peta Jalan Keluar
Kebijakan yang dipercaya pasar berpegang pada tiga pilar.
Pertama, jalur hukum yang tegas. Definisi bank sistemik, metodologi pengenaan levy, tata cara aktivasi golden share, dan prosedur akuisisi—jika diambil—harus dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana yang bisa diuji dan diaudit.
Kedua, kompensasi wajar bagi pemegang saham. Valuasi mesti berbasis parameter yang disepakati dan perlindungan untuk investor ritel diperkuat.
Ketiga, peta jalan keluar yang disiplin. Negara tidak bermalam di ruang yang bukan miliknya; begitu indikator tercapai—stabilitas terjaga, intermediasi produktif menguat, efisiensi layanan membaik—negara wajib melepas kembali kontrol.
Komunikasi yang konsisten dan dapat diverifikasi menjadi lem perekat ketiga pilar, membuat pasar melihat kebijakan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai disiplin.
Arah Pembangunan: Kredit Produktif, Inklusi, dan Efisiensi
Penataan ulang relasi negara dan bank sistemik harus berujung pada manfaat konkret.
Levy yang dirancang benar dapat mengongkosi dana penyangga krisis sekaligus mendorong agenda inklusi.
Hak emas memberi jaminan bahwa keputusan strategis selaras dengan penguatan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan.
Kepemilikan terukur—bila diambil—dapat diikat dengan komitmen layanan publik, misalnya penurunan biaya transaksi, perluasan akses kredit UMKM, dan pengembangan layanan digital yang aman dan inklusif, lalu dilepas kembali ketika sasaran tercapai.
Dengan cara itu, kebijakan tidak berhenti pada simbol intervensi, tetapi bergerak pada perbaikan layanan sehari-hari yang dirasakan masyarakat.
Jangkar yang Menstabilkan, Bukan Beban yang Menenggelamkan
Pada akhirnya, perdebatan akuisisi BCA adalah cermin kedewasaan kita dalam menata hubungan antara kedaulatan kebijakan dan ketenangan pasar.
Pertanyaannya bukan lagi “berani atau tidak berani”, melainkan “mampukah kita merancang kebijakan yang adil dan kredibel.”
Saya berpendapat, langkah korektif yang prospektif, berbasis hukum, berkompensasi wajar, dan memiliki peta jalan keluar yang tegas, bukan saja mungkin, melainkan perlu.
Krisis 1998 telah mengajari kita bahwa ketika negara hadir menyelamatkan sistem, biaya sosialnya luar biasa.
Dua dekade kemudian, keadilan menuntut agar manfaat stabilitas tidak hanya menjadi laba bagi sebagian, tetapi juga dividen bagi publik yang menanggung biayanya.
Jangkar hukum yang terang, tata kelola yang kuat, dan komunikasi yang jernih tidak akan menenggelamkan kapal besar bernama pasar; ia justru menahannya dari arus yang menyesatkan.
Dengan menambah “pintu air” yang tepat, aliran kesejahteraan bisa merata ke lebih banyak sawah.
Di situlah peran negara: memastikan denyut pasar tetap hidup, sambil menjaga agar detaknya mengalir lebih adil menuju kemakmuran bersama.
Pada akhirnya, saya kembali ke pertanyaan semula: benarkah intervensi negara pasti mengacaukan pasar?
Jawaban saya: tidak, selama intervensi itu adalah koreksi prospektif berbasis hukum dengan kompensasi wajar dan peta jalan keluar yang jelas.
Krisis 1998 menuntut rakyat membayar sangat mahal; dua dekade kemudian, keadilan menuntut agar manfaat stabilitas tidak hanya menjadi laba bagi sebagian, tetapi juga dividen bagi yang membiayai keselamatan itu sejak awal: publik.
Saya mendukung kebijakan yang bertopang pada prinsip “keuntungan luar biasa dari status sistemik harus selaras dengan kontribusi luar biasa bagi kepentingan publik.”
Jika itu kita pegang, maka menata ulang relasi negara dengan bank yang pernah diselamatkan bukanlah tindakan yang tak logis.
Itu adalah upaya merawat memori fiskal sekaligus menegakkan moral ekonomi: saat pasar dibantu, pasar pun berkontribusi; saat negara menanggung badai, negara berhak memasang jangkar.