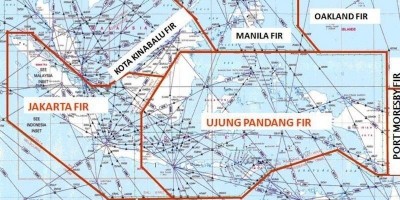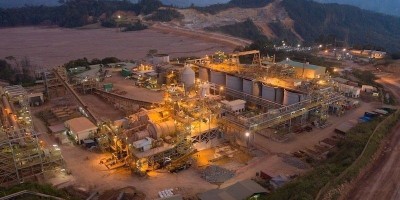Oleh: Darmawan Sepriyossa
Semua kisah itu—SBY, Yanti, Judith, Ramos, Mahathir—bertemu dalam satu simpul: Mbak Tutut adalah potret pemimpin yang memilih berada di belakang, tetapi justru karena itu cahayanya terasa lebih murni.
Malam itu, di Balai Sudirman, banyak kata diucapkan, banyak apresiasi dituliskan, tetapi mungkin yang paling tepat menutup, adalah kata-katanya sendiri, puluhan tahun lalu, kepada majalah Tempo:
"Saya hanya ingin menjadi manusia biasa yang melaksanakan kodrat sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang baik."
JUMAT malam, 15 Agustus 2025, Balai Sudirman, Jakarta, sesak oleh para tokoh bangsa. Ruang besar itu berpendar cahaya lampu kristal, namun ada cahaya lain—lebih lembut, lebih hangat—yang memancar dari sosok perempuan yang sejak lama dikenal dengan panggilan akrab: Mbak Tutut.
Malam itu, ia meluncurkan bukunya, “Selangkah di Belakang Mbak Tutut”. Buku yang judulnya sederhana, tetapi justru menegaskan sikap hidup putri sulung Presiden Soeharto itu: selalu ada untuk ayah, keluarga, dan bangsa, tanpa merasa perlu berada di depan. Di balik kata “selangkah di belakang” ada sebuah filosofi hidup: kesetiaan yang tak tergoyahkan, pilihan untuk tidak pernah menonjolkan diri, dan konsistensi untuk menopang orang lain lebih dahulu daripada dirinya sendiri.
Ruang besar terasa terlalu kecil akibat dipepaki para tokoh bangsa. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam Republik ini, hadir dengan langkah tenang, duduk di deretan kursi depan.
Di sampingnya ada Try Sutrisno, mantan wakil presiden, yang meski telah digerogoti usia, sorot matanya tetap menatap tegas. Jenderal (Purn) Wiranto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua DPD, Menkum Andi Agats, dan banyak tokoh lain mengisi bangku-bangku yang tersusun rapi. Semua datang dengan alasan yang sama: memberi hormat kepada seorang perempuan yang selama ini namanya kerap tenggelam oleh bayangan sang ayah, Presiden Soeharto, padahal kiprahnya berdiri kokoh sebagai dirinya sendiri.
Ketika layar besar di panggung menyalakan wajah Mahathir Mohamad, semua hadirin menahan napas. Mantan perdana menteri Malaysia itu, yang kini berusia seabad, menyampaikan pesan hangat dari Kuala Lumpur. Suaranya bergetar, namun masih penuh tenaga. “Tahniah, selamat, Ibu Tutut,” ujar Dr Mahathir. Intinya, Dr Mahathir menyatakan bahwa Mbak Tutut, “telah memberi arti bagi kata sahabat, bagi kata pemimpin, bagi kata perempuan.”
Tidak banyak yang bisa menahan haru mendengar ucapan itu. Seorang pemimpin yang pernah menjadi wajah Asia di dunia, memberi hormat kepada seorang perempuan Indonesia yang selama ini lebih memilih berjalan selangkah di belakang.
SBY dan Sarapan Panjang di Yogya
SBY membuka kisahnya malam itu dengan nada yang khas: rendah hati, penuh hormat. Pada 1995 itu ia masih Danrem di Yogyakarta. Saat mengawal Presiden Soeharto, ia mendengar seseorang memanggil. “Saya lihat sekeliling, tak ada siapa-siapa. Hanya Mbak Tutut berdiri membuka pintu ruangan besar, tempat Bapak beristirahat. Saya ragu, apakah benar saya yang dipanggil?”
Ternyata benar. “Ayo, temani Bapak sarapan,” ajak Mbak Tutut.
Bagi SBY, itu pengalaman yang tak terlupa. Ia mendapati Pak Harto bercerita panjang soal sejarah negeri, kisah-kisah yang tak pernah dibukukan. Moerdiono, Mensesneg kala itu, berulang kali meminta ajudan mengingatkan. Tapi ajudan, mana berani. Apalagi semua larut dalam suasana akrab yang dipelopori Tutut—sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah dialami seorang perwira menengah kalau bukan karena panggilan ramah putri presiden.
“Sejak itu saya tahu,” kata SBY malam itu, “bahwa Mbak Tutut memang terbiasa ramah, tak memandang pangkat atau jabatan. Ia mendekat bukan untuk dirinya, melainkan untuk menghadirkan orang lain di lingkaran yang lebih hangat.”
SBY menambahkan, saat sama-sama di Panitia Ad Hoc II MPR tahun 1998—membahas ekonomi dan kesejahteraan rakyat—ia menyaksikan sendiri ketekunan Mbak Tutut. “Beliau selalu at her best. Pekerja keras, bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” ujarnya.
SBY menutup kisahnya dengan kenangan lain: empat kali ia bersama Bu Ani Yudhoyono menjenguk Soeharto di RS Pertamina. Selalu, ia mendapati Tutut setia di sisi ayahnya. “Cinta anak pada orangtua itu bukan kata-kata, tapi keteguhan,” ujarnya, sebelum diam beberapa detik, memberi ruang pada ingatan yang mungkin membuat matanya basah. “Saya bersyukur bisa mengantar alm Pak ke peristirahatan terakhir, dengan menjadi pemimpin upacara,” kata SBY.
Kesederhanaan Tutut bukan kisah yang dibuat-buat. Yanti Rukmini, sekretaris pribadinya, menyimpan cerita kecil yang selalu membuat orang tersenyum. Suatu kali Tutut menyerahkan bantuan bagi korban banjir di Jawa Barat. Tubuhnya basah kuyup, lalu seorang warga meminjamkan sarung. Dengan santai ia mengenakannya, lalu naik helikopter. Yanti, yang masih gusar oleh hujan deras, kaget ketika Tutut menyuruhnya duduk di kursi depan, di samping pilot. “Kenapa saya, Bu?” tanyanya gugup. Jawabannya sederhana: “Jadi navigator.”
Malam itu Yanti membantu pilot untuk tetap menelusuri jalan kereta api di bawah. Susah payah, karena hujan lebat yang terus mengguyur kaca heli. Begitulah Tutut, ia membuat orang di sekitarnya berani mengambil peran, bahkan ketika mereka merasa tak mampu.
Judith Dipodiputro, sahabatnya sejak 1990-an, juga punya cerita lain. Saat itu Mbak Tutut menjadi presiden FIODS– Fédération Internationale des Organisations de Donneurs de Sang — atau dalam bahasa Indonesia berarti Federasi Internasional Organisasi Donor Darah. Organisasi ini berdiri tahun 1955, berbasis di Eropa, dan menjadi wadah bagi perkumpulan donor darah sukarela dari berbagai negara.
Pada 1993 itu, di Monaco, usai rapat FIODS, rombongan menunggu taksi. Sebuah mobil mewah berhenti. Penumpangnya, anak pejabat Indonesia, keluar. Ia menyalami Mbak Tutut, menawarkan tumpangan. Mbak Tutut menolak halus, “Saya bersama mereka semua ini,” katanya sambil menunjuk rombongan.
Mobil itu pun melaju. Salah seorang anggota rombongan berbisik sambil tertawa, “Ini yang anak presiden yang mana, yang anak menteri yang mana ya?” Gurauan itu menegaskan kontras: di satu sisi privilese, di sisi lain pilihan sadar untuk tidak mengambilnya.
Sosok Pemimpin yang Kuat
Namun jangan salah kira, di balik kesederhanaan itu, Mbak Tutut dikenal sebagai perempuan dengan kepemimpinan kuat. Ia adalah sosok di balik jalan tol layang pertama Indonesia: Cawang–Tanjung Priok. Infrastruktur yang kini terasa biasa, tapi kala itu sebuah terobosan.
Bahkan pengaruhnya melampaui negeri ini. Fidel V. Ramos, presiden Filipina 1992–1998, menyebutnya langsung: “Madam Siti Hardiyanti Rukmana punya peran penting membantu mengurai kemacetan di Metro Manila awal 1990-an. Terutama di South Luzon Expressway. Saat itu saya ingin menjadikan Filipina macan Asia. Mbak Tutut hadir membawa gagasan dan solusi.”
Jose P. Magno Jr., penasihat militer tiga presiden Filipina, menambahkan: “Anyone will fall in love with her.” Kata-kata itu bukan basa-basi. Ia bicara tentang kharisma yang lahir dari kapasitas.
Tahun 1989, sepulang haji, Mbak Tutut memutuskan tak lagi melepas kerudung. “Yang penting kerudungi hatimu,” pesan ayahnya. Kerudung rajut sederhana yang ia kenakan kemudian menjadi fenomena. Ibu-ibu pasar mencarinya, penjual-penjual menjajakan “kerudung Mbak Tutut.” Ia tidak pernah berniat jadi trendsetter. Tetapi publik melihat konsistensi: sederhana, murah, dipakai tanpa rias berlebihan. Popularitas itu lahir karena kesahajaan, bukan strategi pencitraan.
Di bidang kemanusiaan, Mbak Tutut menorehkan jejak lewat Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI). Ia memimpin periode 1989–1994. Saat itu praktik calo darah merajalela, memperjualbelikan darah yang semestinya gratis.
“Tujuan donor hanya satu: menyelamatkan nyawa orang lain,” ujar Pak Harto saat membuka kongres PDDI 1989.Sebuah pesan yang dijadikan agenda nyata oleh Mbak Tutut. Ia membabat peran calo, memperkuat jaringan donor sukarela. Tegas dan keras, bahkan ketika harus menghadapi kelompok yang terbiasa mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.
Di forum internasional donor darah (FIODS), Mbak Tutut membuat sejarah lain. Ia menjadi presiden tiga periode, memperkenalkan musyawarah mufakat, menggantikan voting. “Sejak berdiri 1955, baru pada era Tutut semua delegasi menerima kepemimpinan seorang wanita muda dari negara berkembang,” tulis salah satu catatan. Ia bahkan memilih makan malam semeja dengan delegasi Portugal di tengah ketegangan soal Timor Timur, menunjukkan bahwa diplomasi bisa dilakukan bukan dengan teriakan, melainkan dengan sepotong roti dan senyum yang tulus.
Diplomasi sunyi itu juga tampak dalam cerita lain. Tahun 1995, beberapa pemuda Timtim melompati pagar Kedubes Portugal, minta suaka. Pak Harto kesal, menyebut mereka boleh pergi kalau ingin hidup di sana. Namun Mbak Tutut diam-diam mengirim selimut biru putih, baju hangat, kebutuhan dasar untuk mereka. “Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa,” pesannya pada Judith. “Nanti kamu dimarahi.” Gestur itu membuka tabir: bahwa ia tidak pernah benar-benar melihat musuh, hanya melihat manusia.
Pak Harto, tiga kali, lewat saran para menteri, meminta Mbak Tutut menjadi menteri. Tiga kali pula ia menolak. Baru pada 1997 ia tak bisa lagi mengelak. Sebelumnya ia bahkan mencarikan pengganti: Inten Soeweno, yang kelak menghentikan judi SDSB. Fakta itu membantah anggapan bahwa Tutut hanya “duduk di kursi karena anak presiden.” Justru sebaliknya, ia berulang kali menolak, memilih bekerja di jalur lain. Soeharto tahu benar, kapan dan di mana putrinya harus ditempatkan.
Semua kisah itu—SBY, Yanti, Judith, Ramos, Mahathir—bertemu dalam satu simpul: Tutut adalah potret seorang pemimpin yang memilih berada di belakang, tetapi justru karena itu cahayanya terasa lebih murni. Malam itu, di Balai Sudirman, banyak kata diucapkan, banyak apresiasi dituliskan, tetapi mungkin yang paling tepat menutup, adalah kata-katanya sendiri, puluhan tahun lalu, kepada majalah Tempo: “Saya hanya ingin menjadi manusia biasa yang melaksanakan kodrat sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang baik.”