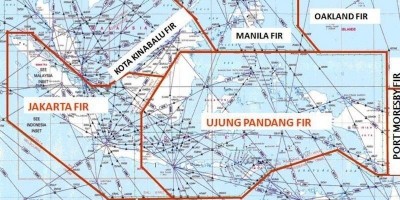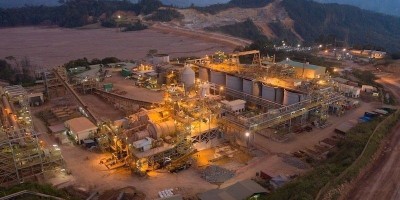Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Kehadiran Adrian Asharyanto Gunadi—mantan CEO Investree—dalam perhelatan internasional di Qatar beberapa bulan lalu, bukan saja memantik kekagetan publik, tetapi juga membongkar satu kenyataan pahit: bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan buronan oleh OJK justru bisa menjalani hidup normal di luar negeri, bahkan menjabat sebagai CEO di JTA Investree Doha.
Sebuah ironi menyakitkan, mengingat di tanah air, ribuan lender meradang karena dana mereka belum kembali, dan kredibilitas industri fintech lending sedang diguncang dari pondasinya.
Jika penegakan hukum adalah panglima, maka kasus Adrian Gunadi adalah ilustrasi gamblang bahwa sang panglima sedang absen dari medannya.
Bagaimana mungkin seseorang dengan status DPO, diklaim telah diajukan red notice oleh otoritas keuangan Indonesia, namun bisa menjalani karier baru secara sah di negara lain?
Hal ini mengindikasikan adanya dua kemungkinan: lemahnya kapasitas diplomasi hukum Indonesia di tingkat internasional, atau minimnya keseriusan dalam melanjutkan proses hukum hingga tuntas.
Dua-duanya menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor fintech, terutama terhadap elite korporasi, belum berjalan maksimal.
Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola, di mana pemain yang melanggar aturan sudah diganjar kartu merah, namun ia masih bebas bermain di lapangan lain, dengan seragam baru, dan tidak ada wasit yang menghentikannya.
Inilah yang terjadi pada Adrian. Dan “lapangan lain” itu adalah Doha, Qatar.
Red notice yang disebut-sebut telah diajukan sejak Desember 2024 oleh OJK dan penegak hukum Indonesia, ternyata belum terdaftar di sistem Interpol hingga pertengahan 2025.
Ini bukan semata perkara teknis. Ini menyangkut wibawa lembaga penegak hukum dan kepercayaan publik kepada sistem keadilan kita.
Ketika publik melihat bahwa seorang tersangka dapat melenggang bebas tanpa konsekuensi, maka pesan yang muncul adalah bahwa hukum di Indonesia bisa dinegosiasikan, atau setidaknya ditunda pelaksanaannya jika pelakunya memiliki akses dan koneksi.
Dampak Terhadap Industri Fintech Lending
Kasus Adrian tidak berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari gunung es kegagalan pengawasan dalam industri fintech lending di Indonesia.
Investree dulunya adalah salah satu pionir platform peer-to-peer lending, bahkan sempat menjadi contoh sukses bagi ekosistem fintech yang sedang berkembang.
Namun, pasca 2023, gelombang aduan datang bertubi-tubi: keterlambatan pembayaran, restrukturisasi kredit yang tidak transparan, hingga potensi gagal bayar yang tidak diantisipasi dengan mitigasi risiko yang memadai.
Ketika regulator akhirnya mencabut izin Investree pada Oktober 2024, itu bukanlah awal penyelesaian, melainkan permulaan kekacauan yang lebih besar.
Karena hingga hari ini, ribuan lender belum mendapatkan kepastian akan pengembalian dana mereka.
Sementara itu, figur kunci yang bertanggung jawab secara etis dan hukum justru membangun karier baru di luar negeri.
Kepercayaan adalah fondasi utama industri fintech.
Tanpa kepercayaan, platform sebesar apapun tidak akan bisa menarik dana masyarakat.
Dan keruntuhan kepercayaan tidak terjadi dalam sehari, namun bisa ambruk seketika ketika satu kasus besar seperti Investree mencuat tanpa penyelesaian. Banyak investor retail yang kini merasa trauma.
Mereka mempertanyakan, apakah OJK sungguh-sungguh mengawasi? Apakah ada jaminan dana mereka akan aman?
Jika kita menggunakan kacamata ekonomi perilaku, kasus ini menciptakan apa yang disebut sebagai “negative anchoring effect.”
Satu pengalaman buruk dengan Investree akan memengaruhi persepsi investor terhadap seluruh industri P2P lending.
Bahkan startup fintech lain yang sehat akan ikut tercemar citranya karena asosiasi negatif yang tidak adil, tetapi sangat manusiawi.
Untuk memperparah situasi, data OJK sendiri menunjukkan bahwa outstanding pinjaman di fintech lending per Mei 2025 telah menurun lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Artinya, bukan hanya kepercayaan yang menurun, tetapi juga likuiditas pasar fintech mulai terkikis. Investor mulai menarik dana mereka atau memilih menahan partisipasi karena merasa ekosistem ini belum aman secara regulasi.
Kejatuhan Investree bisa menjadi “Lehman moment” bagi fintech lending Indonesia jika tidak segera ditangani secara menyeluruh dan transparan.
Ini adalah titik balik yang bisa memicu krisis kepercayaan jangka panjang—bukan karena kerugian itu sendiri, tetapi karena lambannya penegakan hukum dan tidak adanya pertanggungjawaban manajerial dari para pelaku utama.
Rekomendasi
Dalam menghadapi krisis kepercayaan dan kelambanan proses hukum ini, OJK dan penegak hukum perlu bergerak di luar pendekatan administratif semata.
Pertama dan utama adalah transparansi.
OJK perlu membuka kepada publik tentang status red notice Adrian: apakah benar sudah diajukan ke Interpol, apa yang menjadi kendala pengesahannya, dan kapan target waktu untuk pelaksanaannya.
Jangan biarkan publik menebak-nebak dan menjadi mangsa spekulasi liar yang hanya menurunkan kredibilitas institusi.
Kedua, perlu dibentuk tim lintas kelembagaan antara OJK, Kemenlu, Polri, dan PPATK yang fokus pada penelusuran aset (asset tracing) serta diplomasi hukum dengan Qatar.
Jika perlu, dilakukan pembekuan aset di luar negeri melalui Mutual Legal Assistance (MLA). Seringkali, pelaku kejahatan keuangan tidak takut dipenjara, tetapi takut kehilangan aset.
Oleh karena itu, strategi ekonomi harus diutamakan: bekukan asetnya, hentikan fasilitas keuangannya, dan tekan lewat saluran bisnis internasional.
Ketiga, pemerintah perlu meninjau ulang regulasi pendirian entitas fintech di luar negeri yang membawa nama Indonesia.
Kasus Adrian menunjukkan celah besar bahwa seseorang yang bermasalah di tanah air bisa mengembangkan reputasi baru secara legal di luar negeri.
Maka harus ada mekanisme pelarangan atau notifikasi global terhadap individu yang telah diberi sanksi OJK agar tidak bisa menjalankan entitas di yurisdiksi asing tanpa kontrol.
Keempat, kepada masyarakat, OJK perlu segera memfasilitasi pembentukan forum kreditur dan mekanisme pengembalian dana lender.
Bila perlu, dilakukan pengawasan terhadap proses likuidasi aset Investree secara terbuka, dan melibatkan pihak ketiga yang independen. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak sepenuhnya hilang.
Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa fintech bukanlah musuh publik. Justru fintech dapat menjadi solusi inklusi keuangan yang menjangkau mereka yang tak tersentuh perbankan.
Namun, jika industri ini dibiarkan tanpa pengawasan yang tegas dan akuntabilitas hukum yang jelas, maka ia akan menjadi ladang empuk untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian etika bisnis.
Kasus Adrian Gunadi adalah cermin besar yang sedang dihadapkan pada wajah otoritas keuangan dan penegak hukum kita.
Apa yang tercermin bukan sekadar kegagalan individu, tetapi potret kelambanan sistemik dalam merespons kejahatan korporasi di era digital.
Jika kita gagal menangani satu kasus ini, maka kita sedang membuka jalan bagi puluhan kasus serupa untuk muncul di masa depan.
Maka tidak cukup hanya menyebut nama Adrian sebagai tersangka. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ia—dan siapapun yang berada di posisi serupa—tidak bisa lolos dari konsekuensi hukum, tak peduli sejauh apa ia melarikan diri, dan setinggi apa posisi yang ia jabat di negeri orang.
Kepercayaan publik tidak dibangun dari narasi, melainkan dari aksi. Saatnya OJK dan negara membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih memiliki gigi.