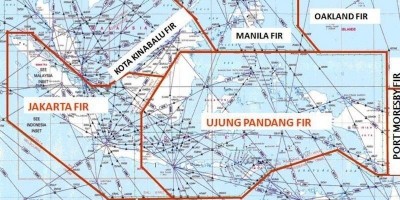Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
APAKAH benar bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kita di tengah tekanan harga yang makin menggila?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik terhadap besaran nominal, tetapi menggugah pemikiran kita tentang arah kebijakan sosial-ekonomi yang diambil pemerintah.
Ketika rakyat harus memilih antara membeli beras atau membayar ongkos anak sekolah, maka kita tahu ada masalah yang lebih mendasar yang tidak bisa diselesaikan dengan angka semata.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp600 ribu yang diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta sebulan sesungguhnya adalah bentuk respons cepat negara terhadap krisis konsumsi rumah tangga kelas pekerja.
Dana ini menjadi embusan napas pendek di tengah udara panas yang makin mencekik.
Dalam jangka pendek, BSU ini memang bisa menghindarkan keluarga dari kelumpuhan daya beli total.
Namun dalam lanskap ekonomi yang lebih luas, kita perlu jujur: bantuan ini tidak cukup untuk mengangkat keluarga pekerja dari jurang kerentanan.
Bayangkan seorang petani yang sawahnya kekeringan parah akibat kemarau panjang.
Lalu pemerintah datang membawa satu tangki air untuk disiramkan ke ladang tersebut.
Air itu jelas bermanfaat, menyelamatkan beberapa tanaman yang hampir mati.
Tapi apakah cukup untuk memulihkan seluruh lahan? Jelas tidak. Tanpa sistem irigasi yang berkelanjutan, tanpa hujan yang merata, air dari satu tangki hanya memberi harapan sesaat.
Begitu pula dengan Bantuan Subsidi Upah. Bantuan ini memang penting sebagai bentuk respons darurat, namun tidak menyentuh akar persoalan yang lebih luas: melonjaknya biaya hidup, tekanan inflasi barang pokok, dan stagnasi pendapatan riil pekerja.
Apalagi ketika kita menyadari bahwa inflasi tak sekadar angka. Ia adalah realitas sosial.
Setiap kali harga cabai, minyak goreng, atau ongkos transportasi naik, yang terdampak paling parah adalah para pekerja informal, buruh pabrik, guru honorer, pedagang kecil, dan jutaan masyarakat urban yang hidup pas-pasan.
Mereka tidak punya tabungan. Mereka tidak bisa menunda konsumsi. Maka ketika harga naik dan pendapatan tetap, pilihan satu-satunya adalah mengurangi konsumsi, menjual aset, atau berutang.
Dan di titik inilah BSU Rp600 ribu hanya mampu menjadi tambalan sementara, bukan pelindung permanen.
Persoalan kita bukan hanya besaran bantuan, melainkan orientasi kebijakan.
Apakah kita hanya ingin memberi bantuan tunai sekali dua kali, atau kita hendak menyusun ulang arsitektur perlindungan sosial yang kokoh dan berkeadilan?
Jika jawabannya adalah yang kedua, maka BSU harus menjadi bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih besar: subsidi kebutuhan pokok, penguatan jaminan sosial, revitalisasi pasar rakyat, dan intervensi harga barang strategis.
Negara tidak cukup hanya hadir memberi uang, tetapi harus memastikan rakyat bisa hidup layak dari hasil kerjanya.
Pemerintah sebetulnya masih memiliki ruang untuk bertindak lebih progresif.
Misalnya, memperluas cakupan penerima bantuan, tidak hanya kepada pekerja formal bergaji di bawah Rp3,5 juta, tetapi juga kepada jutaan pekerja informal dan pelaku UMKM kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Di tengah struktur ekonomi Indonesia yang lebih dari 60 persen informal, pengabaian terhadap sektor ini adalah kealpaan kebijakan yang mahal harganya.
Selain itu, pemerintah bisa menyalurkan subsidi dalam bentuk penguatan pasokan dan pengendalian harga barang pokok.
Alih-alih hanya menyalurkan uang, negara bisa memastikan harga beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan dasar lainnya tetap terjangkau.
Ketika harga stabil, maka uang yang ada di tangan rakyat bisa lebih lama berputar dalam konsumsi.
Artinya, perlindungan daya beli tidak hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga penurunan beban pengeluaran.
Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sistem ekonomi kerakyatan berbasis produktivitas.
Subsidi produktif seperti pelatihan kerja, insentif bagi pengusaha yang menaikkan upah riil, serta dukungan terhadap koperasi dan usaha kecil bisa menjadi strategi jangka menengah untuk mengangkat martabat ekonomi kelas pekerja.
Kita harus mulai memikirkan skema jaminan upah minimum yang mengikuti laju inflasi, agar daya beli tidak terus tergerus.
Dan yang tak boleh dilupakan adalah keadilan dalam akses layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan adalah pengeluaran terbesar rumah tangga miskin.
Jika dua sektor ini bisa diakses secara gratis atau terjangkau, maka ruang fiskal rumah tangga untuk konsumsi lainnya akan terbuka.
Oleh karena itu, memperkuat JKN, memperluas subsidi pendidikan, dan menggratiskan transportasi umum bagi keluarga miskin bukanlah beban anggaran, melainkan investasi sosial yang berdampak jangka panjang.
BSU mungkin memberikan kelegaan sesaat, namun kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan tunai sebagai solusi jangka panjang.
Tugas pemerintah seharusnya lebih dari sekadar membagikan ember air di tengah kekeringan; pemerintah harus membangun sistem irigasi yang mampu mengairi seluruh ladang kehidupan rakyat.
Artinya, kebijakan harus dirancang secara menyeluruh, saling terhubung, dan benar-benar berpihak pada kelompok-kelompok yang paling rentan: pekerja miskin di kota-kota besar, keluarga buruh migran, ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, hingga para pencari nafkah informal yang bertahan hidup dari hari ke hari.
Kita harus mengakhiri paradigma bahwa rakyat hanya perlu dibantu ketika krisis. Negara harus hadir setiap waktu, tidak hanya ketika berita buruk muncul di media.
Keadilan sosial bukanlah hasil dari belas kasih, melainkan buah dari keberpihakan yang dirancang.
Ketika subsidi diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, ketika pasar diatur untuk kepentingan publik, dan ketika APBN dialokasikan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, maka di situlah keadilan sosial menemukan bentuk nyatanya.
BSU Rp600 ribu bisa menjadi titik awal. Tapi ia tak bisa berdiri sendiri.
Kita memerlukan sinergi kebijakan yang tidak hanya menenangkan sesaat, tetapi memulihkan daya hidup rakyat.
Kita memerlukan pemerintah yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Dan yang paling penting, kita memerlukan keberanian politik untuk berpihak, bukan sekadar menyamaratakan.
Sebab dalam masyarakat yang timpang, netralitas hanya memperpanjang ketidakadilan.
Jika hari ini kita percaya bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, maka mari kita bangun sistem yang mewujudkannya.
Bukan dengan janji, tapi dengan kebijakan nyata. Bukan sekadar membagi uang, tetapi memastikan bahwa setiap keluarga punya harapan. Dan bukan hanya menjaga daya beli, tetapi mengangkat martabat hidup seluruh rakyat Indonesia.